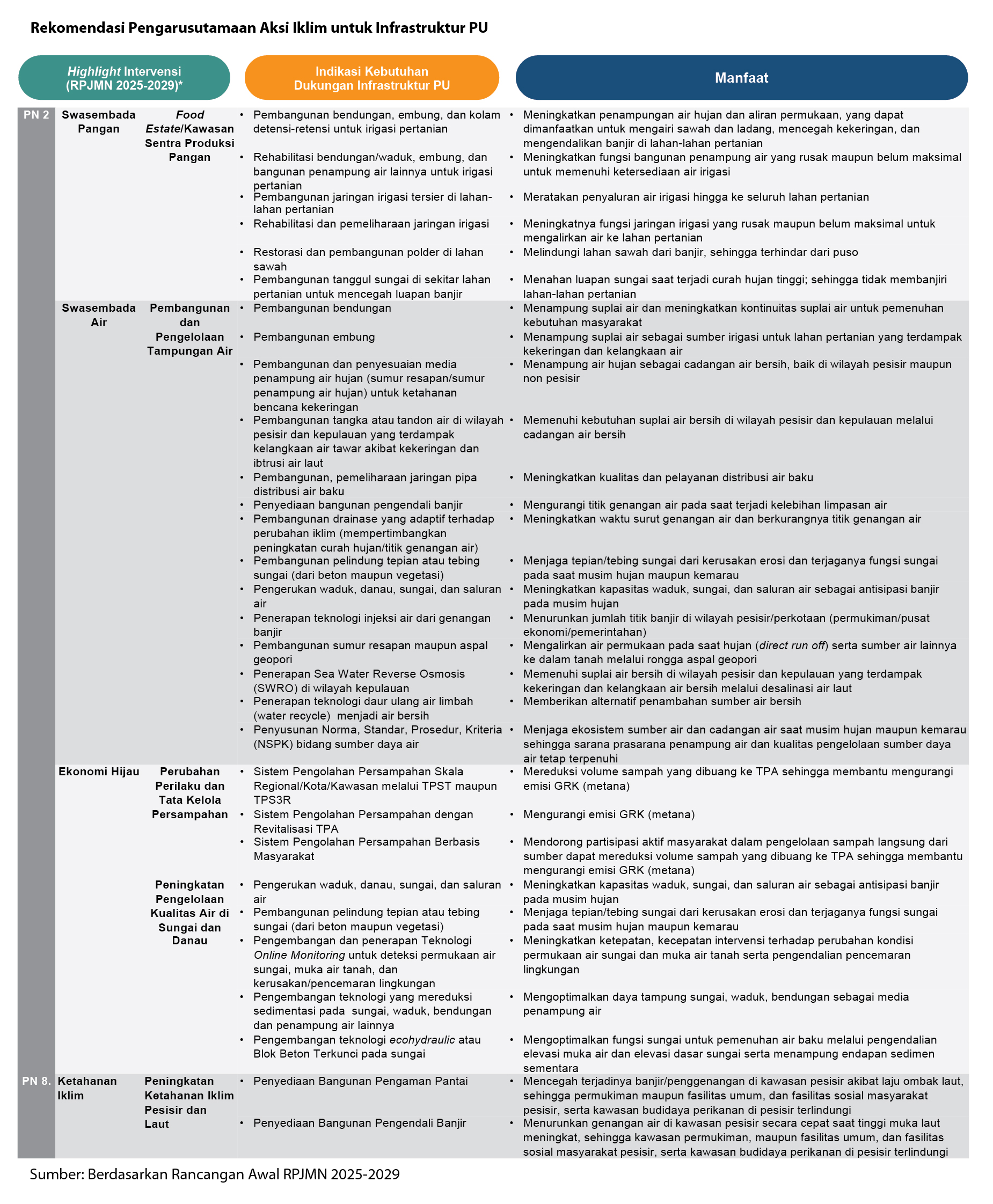Memuat halaman...

Memuat halaman...
50 Artikel

Kawasan yang menjadi proritas penanganan hingga tahun 2034 di Provinsi Jawa Tengah adalah Metropolitan Kedungsepur, PKN Cilacap, dan PKN Surakarta. Isu strategis yang mengemuka adalah Kota Semarang dan Kabupaten Demak memiliki risiko tertinggi karena keduanya merupakan muara DAS besar di Kedungsepur. Sama halnya dengan sistem sungai Semarang Barat dan sistem sungai Dolok Penggaron yang berpotensi rob dan land subsidence. Beberapa rencana aksi yang diusulkan dalam RPIW adalah pembangunan Bendungan bJragung, pembangunan intake dan transmisi Bendungan Jragung di Kabupaten Demak, pembangunan Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal, serta pengendalian banjir.
Rencana aksi yang diusulkan dalam RPIW Provinsi Jawa Tengah telah sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) saat ini. Pertama, pembangunan Bendungan Jragung, saat ini masih berprogres, ditargetkan selesai TA 2025. Bendungan ini merupakan salah satu dari target 61 bendungan dan juga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 tahun 2023.
Kedua, terkait pembangunan intake dan transmisi air baku dari Bendungan Jragung merupakan salah satu yang menjadi perhatian kami. Jadi semua bendungan yang dibangun akan dilanjutkan dengan program pemanfaatannya, baik untuk irigasi, maupun untuk penyediaan air baku. Program penyediaan air baku Bendungan Jragung direncanakan pada tahun 2027 dengan output air baku 1 m3/dt.
Yang terakhir, untuk pembangunan Bendungan Bodrimerupakan salah satu dari target 11 bendungan baru pada periode 2020-2024. Pelaksanaannya diusulkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) sejak tahun 2021. Saat ini progresnya sedang dalam persiapan untuk penyiapan dokumen FBC (Final Business Case) oleh DJPI Dengan kapasitas tampung sekitar 41,82 juta m3, Bendungan Bodri nantinya diharapkan dapat mengairi irigasi seluas 8.861 Hektar, menyediakan air baku sebesar 500 liter/detik, dan mengendalikan banjir sebesar ±6,5 m3/detik.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki isu strategis yang perlu ditangani terkait ketersediaan air, karena provinsi ini berada dalam status melampaui daya dukung air. Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur memang dihadapkan pada tantangan tidak hanya dalam hal penyediaan air baku, juga dihadapkan pada isu perubahan tata guna lahan (banyaknya bekas area tambang yang belum tereklamasi dengan optimal, pembukaan hutan untuk lahan secara liar), sehingga jika tidak segera ditangani dapat mengakibatkan banjir di hilir serta meningkatkan potensi erosi dan sedimentasi di badan air.
Dengan ditetapkannya sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), dokumen pola pengelolaan SDA WS Mahakam juga mengalami penyesuaian, salah satunya dalam hal perhitungan upaya penyediaan air baku, selain untuk IKN sendiri, juga untuk Kabupaten PPU, Kota Balikpapan, dan kawasan penyangga IKN.
Untuk IKN sendiri, Direktorat Jenderal SDA sudah membangun Bendungan Sepaku Semoi yang berpotensi melayani air baku sebesar 2000 liter/detik dan intake Sungai Sepaku dengan kapasitas 3000 liter/detik. Dalam jangka panjang, pemenuhan air baku untuk IKN dapat dipenuhi dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu.
Sementara untuk penyediaan air baku di Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, rencananya akan dilakukan dengan memanfaatkan air Sungai Mahakam. Pada TA 2024 ini kami sedang melaksanakan Studi Kelayakan dan Basic Design Pembangunan Intake Mahakam. Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Balikpapan, akan ada SPAM Regional Balikpapan yang dilaksanakan dengan skema KPBU dan mengintegrasikan sistem tersebut dengan sistem penyediaan air bakunya. Seperti yang diketahui Kota Balikpapan saat ini mengalami krisis air bersih.
Untuk kawasan-kawasan penyangganya, mungkin perlu didefinisikan dan didelineasi terlebih dahulu yang termasuk kawasan penyangga mana-mana saja. Pada prinsipnya kami mendukung pengembangan wilayah dari sisi penyediaan infrastruktur dasarnya, namun juga kami perlu diberikan arah kebijakan pengembangan wilayah-wilayah tersebut akan seperti apa.
Selain itu dari sisi kepariwisataan terutama yang berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Direktorat Jenderal SDA juga turut memberikan dukungan infrastruktur yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa rencana aksi yang diusulkan dalam RPIW atas isu strategis di Sulawesi Selatan diantaranya membangun bendungan untuk penyediaan kebutuhan air baku serta membantu pengaman pantai untuk kawasan wisata yang berisiko abrasi.
Dukungan Direktorat Jenderal SDA untuk pengembangan KSPN biasanya difokuskan pada penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai dari abrasi pada beberapa KSPN yang memiliki lokasi destinasi berupa pantai. Salah satu bentuk dukungan infrastruktur SDA adalah penyediaan air baku untuk daerah Toraja telah pernah kami lakukan melalui peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Air Baku Malillin Kab. Tana Toraja, dengan kapasitas 120 liter/detik.
Untuk KSPN Takabonerate penyediaan airnya masih dalam skala kecil, belum untuk menunjang sebagai kawasan wisata. Ini akan menjadi masukan pemrograman kami ke depan. Sementara untuk Kota Makassar, saat ini sudah terlayani, antara lain melalui Bendungan Bili-Bili sebanyak 2 m3/detik. Ke depannya, jika Bendungan Jenelata selesai, maka salah satu lingkup layanannya adalah Kota Makassar. Untuk pengamanan pantai di Makassar direncanakan secara bertahap sepanjang 1,5 km, dan ini mungkin kami juga harus sinkronkan lagi lokasinya dengan yang dimaksud pada dokumen RPIW.
Secara garis besar Rencana Aksi yang diusulkan dalam RPIW menjadi tantangan tersendiri bagi DJSDA, karena kita tahu RPIW merupakan hasil dari Konreg dan Musrenbangnas yang merupakan hasil pembahasan dengan banyak pihak dan disepakati saat itu, di mana belum ada constraint (batasan nilai-red) dalam hal anggaran atau pagu. Nah, menjadi menarik pada saat pagu atau anggaran yang disediakan dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, tidak mencukupi, kami perlu melakukan penyesuaian.
Penyesuaian tentunya dilakukan dengan menentukan prioritas, karena selain mengakomodir RPIW, hasil Konreg, hasil Musrenbangnas, dll, seringkali ada beberapa direktif atau arahan baru yang tidak atau belum masuk ke dalam rencana pemrograman sebelumnya. Ada lagi beberapa program yang berlanjut dari tahun sebelumnya atau merupakan kontrak tahun jamak, sehingga merupakan anggaran yang mengikat.
Untuk mengawal agar arahan program RPIW dapat terimplementasi dengan optimal, ada beberapa hal yang kami lakukan, seperti:
Mengingat setiap direktorat jenderal mempunyai arahan kebijakan sesuai dengan sektor masing-masing, maka perlu kolaborasi dengan direktorat jenderal Iain di Kementerian PU. Kolaborasi ini juga merupakan tantangan tersendiri, contohnya dalam hal integrasi program penyediaan air baku dengan program air bersih misalnya. Tiap tahun sudah dilakukan sinkronisasi antara kedua direktorat jenderal untuk membahas kebutuhan, kesiapan, dan menyepakati lokasi prioritas yang akan diprogramkan pada tahun perencanaan.
Permasalahan muncul pada saat pagu yang dialokasikan tidak sesuai dengan rencana, sehingga harus dilakukan penentuan prioritas. Pada penentuan prioritas ini seringkali menjadi mengubah hasil sinkronisasi yang sudah disepakati. Memang kolaborasi dan integrasi pemrograman antar-sektor ke depan perlu untuk ditingkatkan. BPIW sebagai koordinator program mungkin dapat memfasilitasi hal-hal seperti ini, termasuk juga dibutuhkan kolaborasi dan integrasi dengan Kementerian Iainnya.
Kami menyambut baik adanya RPIW sebagai pemadu pemrograman antara 4 (empat) Unit Organisasi teknis di Kementerian PU. Sesuai dengan harapan Bapak Menteri PU bahwa infrastruktur yang dibangun harus bermanfaat untuk masyarakat. Dengan keterpaduan pemrograman, maka harapan Bapak Menteri tersebut akan lebih efektif tercapai, semua dipadukan dalam kerangka pembangunan wilayah.
Besar harapan kami agar RPIW dapat menjadi acuan integrasi program di Kementerian PU, sehingga infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan wilayah.
Untuk itu, ke depan BPIW diharapkan dapat mereviu kembali program-program yang menjadi rencana aksi RPIW, dengan mempertimbangkan:

Sektor industri terus menjadi andalan perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja sector ini, salah satu strategi utama yang dilakukan adalah melalui pengembangan wilayah industri, termasuk pembangunan Kawasan Industri (KI).
Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, kegiatan industri diwajibkan berlokasi di kawasan industri. Hal ini menjadikan kawasan industri sebagai solusi strategis untuk menarik investasi, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan konsep ini dapat dilihat di daerah seperti Morowali, Konawe, dan Halmahera Tengah, di mana kontribusi sektor industri melonjak pesat setelah berdirinya kawasan industri.
Karena peran pentingnya, pemerintah telah menetapkan 52 Kawasan Industri Prioritas untuk periode 2019–2024. Kawasan-kawasan ini termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapannya didasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dengan fokus pada pengembangan wilayah berbasis potensi sumber daya dan infrastruktur.
Pengembangan kawasan industri difokuskan pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), yaitu wilayah dengan konektivitas tinggi dan infrastruktur kuat yang dirancang untuk memperkuat hubungan ekonomi regional. Saat ini terdapat 22 WPPI, dan pemerintah berencana menambah tujuh wilayah baru berdasarkan perkembangan industri di tiap daerah. Kawasan di Pulau Jawa difokuskan pada industri berbasis teknologi tinggi, padat karya, dan hemat air.
Contoh suksesnya adalah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah yang telah terisi penuh untuk tahap pertama seluas 450 hektare. Dukungan infrastruktur seperti pelabuhan masih dibutuhkan untuk menarik lebih banyak investor. Di Kendal, kawasan industri telah berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan tingkat okupansi mencapai 80% pada tahap pertama seluas 1.000 hektare. Pengembangan tahap selanjutnya masih membutuhkan infrastruktur pendukung untuk menghadapi lonjakan tenaga kerja. Sementara itu, Kawasan Industri di luar Pulau Jawa diarahkan untuk pengembangan industri berbasis hilirisasi sumber daya alam dan menciptakan pusat ekonomi baru.
Di Kalimantan Timur, Kawasan Industri Buluminung dan Kariangau diarahkan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Walaupun belum masuk dalam RPJMN atau PSN, kawasan ini memiliki potensi besar dengan rencana pengembangan industri kimia, energi rendah karbon, dan logistik.
Di Sulawesi Selatan, fokus pengembangan diarahkan pada industri logam, dengan Kawasan Industri Bantaeng menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional. Kawasan ini memerlukan dukungan infrastruktur logistik agar dapat berkembang lebih cepat dan terhubung dengan wilayah lain.
Tantangan pengembangan kawasan industri meliputi isu pertanahan, tata ruang, infrastruktur, energi, lingkungan, hingga tata kelola. Untuk mengatasinya, Kementerian Perindustrian terus berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait, termasuk Kementerian PUPR, melalui forum dan musyawarah perencanaan pembangunan.
Kami optimis, dengan sinergi dan dukungan yang solid dari semua pihak, pembangunan kawasan industri dapat berjalan optimal dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.(**)

Kementerian Pertanian memiliki pendekatan teknoratik infrastruktur untuk pengembangan lokus pertanian di kawasan pertanian Bone-Wajo-Sidrap-Pinrang di Sulsel dan Jateng sebagai lumbung padi terbesar kedua di Indonesia.
Berdasarkan visi-misi presiden terpilih yang telah diterjemahkan dalam RPJMN, maka pendekatan teknokratik yang digunakan sebagai dasar pembangunan pertanian ke depan adalah pertanian tidak lagi dilihat sebatas kegiatan untuk memproduksi bahan mentah, tetapi juga diarahkan untuk pada penciptaan nilai tambah dan hilirisasi yang terintegrasi.
Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat industri pengolahan secara merata di Indonesia dan pada gilirannya dapat menciptakan pemerataan pembangunan pertanian. Aspek penting lainnya dari pendekatan ini adalah terciptanya pertumbuhan sentra-sentra produksi baru yang akan berperan memastikan kecukupan pangan di wilayahnya, menjamin stabilitas harga, dan pada gilirannya dapat menekan laju inflasi pangan, termasuk di sentra-sentra pangan di Sulsel dan Jateng.
Untuk memastikan terbangunnya kerangka fondasi yang dapat memaksimalkan peran sektor pertanian dalam transformasi ekonomi, diperlukan skenario yang komprehensif yang dituangkan dalam kerangka strategis pembangunan pertanian. Sasaran utama yang ingin dicapai selama 2025–2029 adalah terciptanya Pertanian Maju Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia. Sasaran tersebut dicapai melalui program: (a) Pertumbuhan skala dan jumlah usaha pertanian (b) Kemandirian pangan asal pertanian (c) Ketersediaan bahan baku bionergi (d) Penciptaan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan (e) Peningkatan kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular.
Kelima program tersebut dalam implementasinya didukung oleh enam kegiatan utama yang saling terkait, yaitu (a) transfomasi petani (b) pengembangan kawasan sentra produksi pangan dengan penerapan teknologi pertanian modern berkelanjutan (c) fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pertanian (d) peningkatan sistem kesehatan hewan (e) pengawasan kepatuhan tata kelola pertanian berkelanjutan dan (f) hilirisasi komoditas pertanian.
Keenam pendekatan tersebut (utamanya pengembangan kawasan sentra produksi pangan) membutuhkan dukungan infrastruktur dasar untuk berbudidaya tanaman, seperti lahan, jaringan irigasi dan tata air, bendungan, jalan usaha tani dan sarpras lainnya.
Ketujuh pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian.
Strategi pengembangan lokus-lokus pertanian
Penyusunan Renstra Kementerian Pertanian Menuju Lumbung Pangan Nasional ditujukan sebagai acuan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah di bidang pangan dan pertanian dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program Pembangunan Pangan Dan Pertanian Tahun 2025– 2029. Tujuan pembangunan pertanian pada tahun 2025- 2029 adalah: (1) mencapai kemandirian energi, pangan, dan mewujudkan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia (2) memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan energi secara berkelanjutan (3) meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui hilirisasi hasil pertanian, dan (4) meningkatkan kesejahteraan petani.
Pembangunan pertanian dengan pendekatan kawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, yang selanjutnya pengembangan lokus tersebut disesuaikan dengan potensi komoditas yang ada dimasing-masing provinsi sesuai dengan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, dimana provinsi Sulsel, Jateng dan Kaltim sebagai kawasan padi nasional. Kawasan pertanian nasional tersebut dikembangkan untuk komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian.
Kebijakan dan program Kementan di Jateng, Kaltim dan Sulsel
Secara umum program pembangunan pertanian di ketiga lokasi tersebut dilakukan melalui: i) intesifikasi dan ekstensifikasi, ii) perbaikan jaringan irigasi, iii) pemenuhan benih/bibit unggul dan pupuk, iv) bantuan alsintan untuk pertanian modern, dan penguatan kelembagaan petani. Kegiatan intensifikasi adalah strategi untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi lahan sawah eksisting, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: a). Peningkatan indeks pertanaman (IP) padi yang didukung dengan mekanisasi prapanen dan panen (mempercepat olah tanah setelah panen) dan pompanisasi (jaminan ketersediaan air). b). Menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat 150 ribu ton yang meliputi 5 juta hektar dan pupuk yang mudah diakses petani melalui pengembangan benih unggul. c). Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) d). Penggunaan alsintan panen dan pascapanen modern untuk mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan rendemen menuju transformasi pertanian tradisional ke modern.
Strategi, program dan kebijakan pembangunan pertanian di Jateng, Sulsel dan Kaltim dilakukan oleh masing-masing eselon I Kementan, seperti Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen PKH, Ditjen Perkebunan, Ditjen PSP dan Eselon I lainnya. Secara umum program tersebut meliputi:
1) Optimalisasi peningkatan indeks pertanaman padi, 2) Pengembangan padi, 3) Pengembangan jagung, kedelai dan pangan lokal, 4) Pengembangan sistem perbenihan, 5) pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penanganan dampak perubahan iklim, dan 5) Alsintan pengolahan dan pascapanen.
Total anggaran APBN tahun 2024 di Jateng sebesar Rp 509,690 milyar, di Sulsel sebesar Rp 425,222 milyar. Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional dengan potensi pengembangan komoditas: Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu) hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih, jeruk, pisang, mangga, manggis, durian) perkebunan (kelapa, tebu, kopi, teh) dan peternakan (sapi potong, babi, ayam buras).
Provinsi Kalimantan Timur serdasarkan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional dengan potensi pengembangan komoditas: Tanaman Pangan (padi, jagung) hortikultura (cabai, bawang merah, jeruk, pisang) perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, lada) dan peternakan (sapi potong, sapi perah, domba dan itik).
Provinsi Sulawesi Selatan serdasarkan Kepmentan 472 Tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional dengan potensi pengembangan komoditas: Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu) hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih, pisang, manga, manggis, durian) perkebunan (tebu, kakao, kopi, lada, pala, cengkeh) dan peternakan (sapi potong, kerbau, sapi perah dan ayam buras).
Program Kementan lima tahun kedepan
Dalam penyusunan program dan kebijakan dengan pendekatan pengembangan kawasan pertanian. Strategi yang digunakan untuk memastikan keberlanjutan program tersebut dapat berjalan adalah dengan membuat gugus tugas disetiap lokus. Gugus tugas tersebut terdiri dari penjab dari eselon I dan anggotanya dari eselon II lingkup Kementan. Gugus tugas tersebut bertugas melakukan pendampingan dan turun langsung ke lokasi kegiatan, memonitor dan melaporkan capaian kegiatan yang dilakukan daerah setiap hari kepada Menteri Pertanian.
Selain itu akan dilakukan refocussing dan dukungan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pada lokus-lokus tersebut utamanya terkait dengan optimasi lahan, ketersediaan benih dan pupuk, dukungan alsintan pra dan pasca panen, serta dukungan kelembagaan usaha tani.
Dukungan infrastruktur PUPR
Air merupakan kebutuhan vital dalam usaha budidaya pertanian, untuk itu perlu adanya harmonisasi dan sinergi dalam penyediaan sumber-sumber air untuk pertanian.
Hal yang perlu diperhatikan agar dukungan infrastruktur PUPR dapat bermanfaat mendukung ketahanan pangan adalah : 1) Lokasi infrastruktur berada pada lokasi sentra/kawasan pengembangan pangan, 2) Adanya kelembagaan petani yang memanfaatkan infrastruktur tersebut terkait bagaimana pengelolaan dan keberlanjutannya, dan 3) Anggaran operasionalisasi dan maintenance sarana tersebut.
Perlu koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait identifikasi saluran tersier pembangunan baru (kewenangan PUPR) dan saluran tersier eksisting yang bisa direhab/ditingkatkan fungsinya (Kementerian Pertanian bisa ikut melakukan rehabilitasi/peningkatan fungsi), sehingga infrastruktur yang dibangun oleh PUPR sejalan dengan lokasi-lokasi pengembangan tanaman pangan utama sehingga dapat langsung dimanfaatkan.
Sebagai contoh untuk optimalisasi pemanfaatan bendungan baru melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada saluran tersier eksisting dalam rangkaian jaringan irigasi bendungan baru.
Terkait dengan pemanfaatan bendungan, saat ini pemanfaatan bendungan untuk pertanian dilaksanakan pada bendungan baru dengan status jaringan primer dan sekundernya telah terbangun, yaitu pada 12 bendungan baru dari 61 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR, dengan luas layanan ± 108.469 Ha.
Program dan lokus prioritas Kementan
Sektor pertanian yang telah terbukti sebagai bantalan ekonomi saat terjadi krisis, mempunyai kedudukan yang teramat vital dan fatal. Vital karena sektor pertanian sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan fatal apabila penyediaannya defisit lantas dapat dijadikan alat oleh kekuatan politik, baik yang sedang berkuasa maupun yang di luar kekuasaan saat ini. Selain sebagai penyedia bahan pangan, sektor pertanian juga mempunyai peran strategis sebagai sumber bahan bahan baku industri, sumber penerimaan devisa, dan penyedia lapangan kerja.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen per tahun selama kurun waktu 2025- 2029, maka sektor pertanian minimal harus tumbuh sebesar 4,81 persen per tahun dan fokus pada lima program utama, yaitu: a). Program Swasembada Pangan Nasional b). Pengembangan Komoditas Ekspor Strategis c). Peningkatan Produksi Susu untuk Mendukung Program Makan Bergizi d). Program Pekarangan Pangan Bergizi dan e). Program Mandiri Energi B-50.
Kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, adalah: 1) optimalisasi lahan rawa 2) pompanisasi lahan tadah hujan 3) cetak sawah swakelola 4) pertanian modern 5) dukungan program makan siang bergizi gratis 6) penguatan penyuluh pertanian dan 7) hilirisasi komoditas pertanian.
Guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Indonesia, baik di pasar domestik maupun global, pembangunan pertanian ke depan. Hilirisasi akan mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal sehingga akan tercipta peningkatan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Selama ini sektor pertanian ternyata mampu menggerakan sektor ekonomi hulu (penyedia input) maupun hilir (sebagai input antara).
Lokus pengembangan sentra produksi pangan adalah cetak sawah di Kalteng, Sumsel, Kalbar, Kaltim dan Papua Selatan. Program cetak sawah 3 juta hektar akan dilakukan selama 3 tahun, dimana pada tahun pertama akan dilakukan seluas 1 juta hektar di provinsi Papua Selatan, Kalsel, Kalteng, dan Sumsel.
Keselarasan program RPIW dan Kementan
Konteks pembangunan pertanian yang notabene berlokasi diperdesaan fokus pada tiga aspek : ketersediaan infrastruktur dasar, kualitas SDM dan pemanfaatan inovasi teknologi. Pemenuhan pada 3 aspek dasar tersebut akan berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja perdesaan, pengurangan senjang desa-kota, pengurangan kemiskinan dan laju urbanisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Upaya yang dilakukan Kementan untuk meningkatkan produksi pertanian adalah melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, pengendalian alih fungsi lahan, dukungan kebijakan dan pengembangan sarana prasarana pertanian seperti lahan usaha tani, jalan usaha tani, jaringan irigasi, benih dan pupuk yang beberapa terkait dengan program di PUPR.
Sampai saat ini ada beberapa program infrastruktur PUPR belum selaras dengan program di Kementan. Hal ini disebabkan karena:
1) Pembangunan beberapa infrastruktur seperti bendungan belum disertai pembangunan saluran pendukung ke lahan seperti irigasi primer, sekunder dan tersiernya, sehingga upaya peningkatan produksi pangan peningkatan IP menjadi terkendala. 2) Saat musim kemarau debit air bendungan.
2) Saat musim kemarau debit air bendungan turun sehingga tidak dapat digunakan oleh petani pada saat musim tanam
3) Minimnya anggaran/kegiatan pemeliharaan sarpras irigasi dan jalan usaha tani
4) Adanya persaingan pemanfaatan sarpras antar sektor pertanian dengan sektor lainnya seperti perhubungan, perikanan dan lainnya, sehingga pemanfaatan infrastruktur irigasi menjadi tidak optimal.
Beberapa saran dan tindak lanjut:
1) Perlu koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait identifikasi saluran tersier pembangunan baru (kewenangan PUPR) dan saluran tersier eksisting yang bisa direhab/ditingkatkan fungsinya (Kementerian Pertanian bisa ikut melakukan rehabilitasi/ peningkatan fungsi)
2) Optimalisasi pemanfaatan bendungan baru melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier pada saluran tersier eksisting dalam rangkaian jaringan irigasi bendungan baru.
3) Kegiatan irigasi pertanian berupa pengembangan jaringan irigasi di tingkat tersier namun perlu audit bersama antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian untuk identifikasi data irigasi (kondisi saluran irigasi primer, sekunder dan tersier).
4) Koordinasi meliputi: percepatan pemanfaatan bendungan baru, peningkatan fungsi saluran tersier dan penetapan CPCL yang bersinggungan antara program PUPR dan Kementan.(**)
Rubrik Perspektif Buletin Sinergi Edisi 63 menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan. Dalam rubrik ini dibahas dukungan infrastruktur dari Kementerian Keuangan untuk pengembangan kawasan pertanian, Topik ini mencakup peningkatan produktivitas, pemerataan pertumbuhan, dan ketahan pangan berkelanjutan.. selengkapnya dalam Rubrik Perspektif Buletin Sinergi Edisi 63.
RPIW Selaras dengan Prioritas Sektor Pertanian
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si.
Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Pertanian

Pariwisata merupakan salah satu potensi utama penerimaan negara. Terkait hal itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) merekomendasikan dukungan infrastruktur PUPR yang diarahkan untuk pengembangan lokus-lokus pariwisata seperti Kepulauan Derawan di Provinsi Kalimantan Timur, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur, KSPN Dieng, dan Kepulauan Karimunjawa di Provinsi Jawa Tengah, serta Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Toraja-Makassar-Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dokumen RPIW ini disusun dengan pendekatan teknokratik untuk perencanaan 5 tahun ke depan.Terkait hal itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) mengapresiasi berbagai dukungan yang telah diberikan oleh Kementerian PUPR terhadap perkembangan destinasi pariwisata di Indonesia, termasuk penyusunan Dokumen RPIW oleh BPIW yang merekomendasikan dukungan infrastruktur PUPR diarahkan terhadap pengembangan destinasi pariwisata yang selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.
Selain itu, sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pengelolaan destinasi sangat penting, terutama di KSPN dan 10 DPP serta destinasi lainnya seperti Toraja-Makassar-Selayar, Kepulauan Derawan dan lain-lain.
Dukungan infrastruktur dari Kementerian PUPR tersebut, baik dalam bentuk jalan dan infrastruktur dasar seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat menunjang pengembangan aksesibilitas dan amenitas di destinasi pariwisata. Merujuk pada tugas dan fungsi kami, berbagai program/kegiatan yang kami laksanakan juga berfokus dalam memberikan pendampingan pengelolaan destinasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dengan pendampingan ini, kami memastikan bahwa pengelola destinasi mampu memanfaatkan infrastruktur yang ada dengan optimal, mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan, dan meningkatkan daya tarik destinasi. Kemenparekraf/Baparekraf terus berperan aktif dalam memberikan dukungan strategis di berbagai destinasi, khususnya di lokus Destinasi Pariwisata Prioritas.
Pengembangan destinasi pariwisata sangatlah penting terhadap perkembangan aspek ekonomi lokal, lingkungan, serta sosial budaya masyarakat. Pada Tahun 2023, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Pariwisata mencapai 3,9% dengan penyerapan tenaga kerja pariwisata sebesar 24,41 juta orang dan tenaga kerja ekonomi kreatif sebesar 24,92 juta orang.
Kondisi ini menggambarkan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang sangat potensial untuk mendukung pengembangan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar, terdapat tiga aspek yang perlu didukung, yaitu pengembangan atraksi, amenitas dan aksesibilitas di destinasi pariwisata yang akan meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan mewujudkan kenyamanan wisatawan dalam berwisata, sehingga dapat menambah jumlah wisatawan, lama tinggal dan tingkat pengeluaran wisatawan (spending), sebagaimana yang telah kami rasakan bersama di DPSP Borobudur dan Penataan KSPN Dieng pada Tahun 2020-2024.
Isu Strategis Pengembangan Lokus Pariwisata
Berdasarkan Rencana Strategis yang telah disusun dan hasil identifikasi terhadap kondisi eksisting, terdapat beberapa isu strategis utama terkait Pengembangan Destinasi Pariwisata di KSPN Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, KSPN Dieng dan KSPN Karimunjawa, meliputi Perubahan iklim dan Mitigasi Bencana, Konektivitas dan Dukungan Infrastruktur Pariwisata, Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di sekitar destinasi pariwisata, serta Kemudahan Investasi. Selanjutnya, dalam pengembangan destinasi pariwisata, khususnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, terdapat beberapa isu strategis yang harus diatasi, seperti ketergantungan pada wisata alam; pengelolaan daya dukung lingkungan; dan peningkatan kualitas layanan. Sebagai contoh, di Bali muncul isu overtourism, sementara di destinasi seperti Labuan Bajo dan Raja Ampat, tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan.
Pendampingan pengelolaan destinasi dan peningkatan kapasitas SDM lokal juga menjadi fokus Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf. Pada saat kegiatan pendampingan ini juga diperoleh masukan-masukan mengenai isu terbaru yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan pengelola dalam mengelola arus wisatawan, menjaga kelestarian alam, dan mempromosikan pariwisata berbasis komunitas serta digital.
Selanjutnya, pengembangkan lokus-lokus pariwisata tidak hanya difokuskan dari sisi pariwisata saja, namun juga dari sisi ekonomi kreatif yang salah satunya adalah melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif. Hal ini dilaksanakan oleh Kemenparekraf/ Baparekraf melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur yang salah satu tugas fungsinya adalah melaksanakan program Pengembangan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia.
Sebagai bagian dari program ini adalah kegiatan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) dimana kabupaten/kota dibantu untuk menemukenali subsektor ekonomi kreatif unggulan daerah sebagai dasar dan pertimbangan perancangan peta jalan pengembangan ekonomi kreatif daerah maupun pengembangan daerah secara garis besar. Saat ini dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sebanyak 83 kabupaten/kota sudah masuk dalam ekosistem KaTa Kreatif Indonesia dan 41 kabupaten/kota diantaranya telah ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia.
Beberapa kabupaten/kota yang sudah ditetapkan menjadi KaTa Kreatif Indonesia antara lain, Kota Makassar, Kabupaten Wonosobo, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dll. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sudah PMK3I namun belum ditetapkan menjadi KaTa Kreatif Indonesia, diantaranya Kota Samarinda, Kabupaten Kulon Progo, dll. Kebijakan, Strategi, dan Program Pengembangan Pariwisata di Tiga Provinsi
Kemenparekraf/Baparekraf terus menjalin koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur dan pengelolaan destinasi pariwisata. Dalam forum seperti Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran dan Musrenbangnas, kami memastikan bahwa program pengembangan destinasi pariwisata dapat berjalan selaras dengan dukungan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Selain itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, DPSP Borobudur (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta) termasuk dalam destinasi prioritas yang perlu didukung perkembangannya sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terutama pengembangan atraksi, amenitas dan aksesibilitas. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur juga menyelenggarakan beberapa program unggulan untuk mendukung pengembangan pariwisata di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi:
Kemenparekraf/Baparekraf juga memiliki Badan Pelaksana Otorita Pariwisata (BPOP) di beberapa lokasi, seperti BPOP Danau Toba, BPOP Borobudur, dan BPOP Labuan Bajo Flores. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas atraksi dan amenitas di Kawasan Otoritatif. Kemenparekraf/Baparekraf juga melakukan fasilitasi penyusunan Dokumen Desain, Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Desa Wisata Terpadu, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM, Penguatan Jejaring dan Kemitraan, Pendampingan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pariwisata.
Upaya Mensinergikan Program Antar Kementerian
Upaya Kemenparekraf/Baparekraf dalam mensinergikan program dalam 5 tahun ke depan dilakukan melalui beberapa langkah strategis yakni:
Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Pariwisata dapat secara efektif mensinergikan program pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata antar kementerian/lembaga, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan kenyamanan destinasi pariwisata dalam lima tahun ke depan.
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Agar Dukungan Infrastruktur PUPR Bisa Memberikan Manfaat Optimal
Dukungan infrastruktur fisik perlu diimbangi dengan dukungan non-fisik, guna mewujudkan keseimbangan antara dukungan infrastruktur pariwisata dan kapasitas SDM Pengelola. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti:
Seluruh langkah-langkah pengembangan tersebut harus dilaksanakan dengan kolaborasi pentahelix. Sesuai arahan Menparekraf/Kabaparekraf pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mengedepankan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kolaborasi pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media menjadi penting dalam menjamin kebermanfaatan dan dampak yang lebih luas serta dalam merumuskan solusi yang tepat sasaran dan tepat guna dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berkualitas.(**)

Selama periode RPJMN 2020 - 2024, Kementerian PUPR telah melaksanakan berbagai proyek infrastruktur dalam rangka mendukung pencapaian target RPJMN 2020-2024. Proyek-proyek tersebut secara positif berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa proyek infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PUPR yang memiliki kontribusi yang signifikan terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua.
Proyek seperti Bendungan Manikin dan Temef di NTT, serta pembangunan jalan Trans Sumba, Trans Maluku, dan Trans Papua menjadi bagian penting dari upaya untuk memperkuat ketahanan air dan pangan, serta membuka keterisolasian wilayah terpencil dan meningkatkan akses ke pelayanan dasar. Hal ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.
Pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan strategis seperti DPP Labuan Bajo, DPP/KEK Morotai, DPP Raja Ampat, dan KEK Sorong juga telah dilakukan diantaranya melalui penataan kawasan pariwisata, pemenuhan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan, dan penyediaan air baku, yang semuanya akan memperkuat daya tarik wisata kawasan-kawasan tersebut, sekaligus mendukung kesejahteraan penduduk.
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara juga telah dilakukan di perbatasan seperti Napan, Motamasin, dan Skouw, yang tidak hanya memperkuat keamanan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Di Wilayah Papua, sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan daerah di Daerah Otonom Baru (DOB), pembangunan gedung pemerintahan seperti Kantor Gubernur, Kantor MRP, dan Kantor DPRP, serta infrastruktur pendukungnya menjadi hal yang krusial.
Kementerian PUPR bersama kementerian/lembaga terkait berkomitmen untuk mendampingi pemerintah daerah dalam setiap tahap perencanaan dan pembangunan kawasan inti pemerintahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Namun demikian, wilayah NTT, Maluku, dan Papua masih menghadapi tantangan besar. Masalah seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta ketimpangan konektivitas antarwilayah menjadi penghambat utama pengembangan wilayah. Selain itu, desentralisasi yang belum optimal dan tingginya ketergantungan pada transfer ke daerah memperlambat kemandirian fiskal di daerah-daerah ini. Pengelolaan dana otonomi khusus di Wilayah Papua juga belum efektif, namun terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan dana otsus yang sesuai untuk menjawab akar masalah pembangunan.
Provinsi NTT, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua juga menghadapi risiko bencana hidrometeorologi dan geologi mengingat sebagian wilayah tersebut dilalui jalur patahan serta gunung api aktif. Wilayah-wilayah ini juga banyak didiami oleh masyarakat hukum adat yang saat ini perlindungannya masih belum maksimal. Di samping itu, dampak perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani.
Untuk menjawab isu strategis tersebut, RPJPN 2025-2045 disusun dengan menitikberatkan upaya-upaya transformatif di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu sasaran Visi Indonesia Emas 2045, yaitu target kontribusi PDRB KTI mencapai 28,5%, dan meningkat dari proyeksi baseline sebesar 21,4% di tahun 2025.
Untuk mencapainya, pendekatan transformatif dilakukan melalui pengembangan ekosistem sentra produksi, riset berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan konektivitas fisik dan digital.
Sebagai upaya mencapai target tersebut, telah disusun kebijakan transformatif yang spesifik untuk menjawab isu di Provinsi NTT, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua sesuai konteks wilayah masing-masing. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, masing-masing provinsi di wilayah-wilayah ini diarahkan untuk mengembangkan ekosistem sentra produksi, industri, dan riset inovasi berbasis komoditas unggulan.
Sedangkan untuk optimalisasi pengembangan potensi pariwisata, perlu dilakukan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, serta amenitas di kawasan pariwisata prioritas eksisting seperti DPP Labuan Bajo, Raja Ampat, dan Morotai, serta kawasan pariwisata lainnya, di antaranya Banda Neira di Provinsi Maluku, Anggi di Provinsi Papua Barat, serta Pulau Sumba di Provinsi NTT.
Termasuk dalam upaya transformasi ekonomi ini adalah pengembangan kawasan sekitar kawasan strategis eksisting seperti KI Teluk Weda dan KI Fak Fak, pembangunan infrastruktur pemerintahan dan perkotaan di 4 ibukota DOB, serta penataan dan pengembangan perkotaan prioritas dengan masterplan yang disusun oleh Bappenas, yaitu Weda (Kab. Halmahera Tengah), Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat), Daruba (Kab. Pulau Morotai), Anggi (Kab. Pegunungan Arfak), Banda Neira (Kab. Maluku Tengah), dan Kota Sorong.
Peningkatan kualitas SDM juga menjadi pilar utama pembangunan ke depan. Langkah-langkah seperti sekolah berpola asrama, sekolah sepanjang hari, dan sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka serta pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) dan sistem telemedicine berbasis gugus pulau dirancang untuk menjawab tantangan geografis. Upaya ini diharapkan dapat menekan prevalensi stunting, meningkatkan angka partisipasi pendidikan, serta memperluas akses layanan kesehatan.
Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian utama. Pendekatan smart government dan peningkatan kapasitas ASN akan menjadi strategi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, penguatan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kecamatan perbatasan prioritas, dan pulau-pulau kecil terluar serta pemberantasan praktik ilegal seperti IUU Fishing merupakan langkah penting untuk menjaga kedaulatan wilayah dan sumber daya alam.
Dalam peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan diversifikasi pangan berbasis tanaman pangan, pangan akuatik dan pangan hewani menjadi prioritas utama. Dukungan infrastruktur seperti penyediaan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan peningkatan ketersediaan air baku akan menjadi landasan bagi ketahanan pangan, air, dan energi yang berkelanjutan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas serta perumahan dan permukiman untuk mendukung upaya pembangunan transformatif di Provinsi NTT, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua tersebut.
Pembangunan infrastruktur ini tentunya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan akses ke pusat-pusat pertumbuhan, mendukung pengembangan komoditas unggulan wilayah, serta menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga akan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang mengacu pada RPJPN dan RPJMN merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara perencanaan infrastruktur wilayah dengan kebijakan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang, memastikan bahwa perencanaan infrastruktur tidak hanya bersifat regional atau sektoral, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan nasional.
Bappenas tentu berharap bahwa dalam penyusunannya, substansi RPIW perlu selaras dengan substansi RPJPN dan RPJMN, terutama terkait arah kebijakan pembangunan dan lokasi prioritasnya. Dengan mengacu pada RPJPN dan RPJMN, BPIW memastikan bahwa perencanaan infrastruktur wilayah tidak hanya bersifat regional atau sektoral, tetapi juga mendukung tujuan-tujuan pembangunan nasional. Hal ini sangat penting agar setiap pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak yang terbatas, tetapi juga berkelanjutan dan sejalan dengan visi pembangunan Indonesia, yakni Visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, RPIW yang menjadi input dalam pelaksanaan Rakorbangwil dan Konreg menunjukkan adanya proses bottom-up dan top-down yang saling menguatkan dalam perencanaan infrastruktur. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas daerah dapat diakomodasi dalam perencanaan yang dilakukan di tingkat pusat, sehingga pelaksanaan infrastruktur benar-benar mendukung pembangunan berbasis wilayah.
Selain RPJPN dan RPJMN, RPIW juga diharapkan dapat mengacu pada dokumen nasional yang bersifat kewilayahan, seperti Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 beserta turunannya (Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua), Rencana Induk Percepatan Pembangunan Pulau Sumba 2023-2042, serta masterplan penataan dan pengembangan kawasan perkotaan prioritas.
Pada akhirnya, ketika RPIW menjadi input dalam pelaksanaan Rakorbangwil dan Konreg, diharapkan seluruh dukungan kegiatan yang dibahas sudah selaras, baik dari sisi prioritas kegiatan maupun lokasi prioritasnya. Hal ini perlu dikawal dengan seksama agar dapat termuat dalam Renja Kementerian PUPR.
Kemudian Kementerian PUPR merupakan counterpart Bappenas dalam pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Bappenas berharap, sebagai institusi perencanaan infrastruktur wilayah, BPIW dapat memainkan peran penting dalam mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis wilayah.
Harapannya BPIW dapat berperan dalam merencanakan dan menyusun strategi pengembangan infrastruktur yang terkoordinasi dengan rencana pembangunan nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan konektivitas antarwilayah.
Selanjutnya, salah satu fokus utama dari Visi Indonesia Emas 2045 adalah peningkatan konektivitas, baik fisik maupun digital. BPIW diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan jaringan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan wilayah terpencil guna mendukung integrasi ekonomi nasional.
Kami menekankan bahwa BPIW diharapkan turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur yang ramah lingkungan, mendukung ketahanan terhadap perubahan iklim, serta berkelanjutan untuk jangka panjang, sesuai dengan agenda pembangunan hijau yang menjadi bagian dari visi ini.
Dalam mendukung pemerataan pembangunan, BPIW dapat mengoordinasikan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memajukan daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Selain itu, kami berharap BPIW Kementerian PUPR terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa pengembangan infrastruktur berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah dan selaras dengan prioritas nasional.
Dengan peran ini, BPIW Kementerian PUPR dapat menjadi salah satu institusi yang sangat penting dalam mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(**)

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Menurut Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas terhadap kinerja pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 menunjukkan bahwa secara garis besar telah menunjukkan hasil yang baik. Bahkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda dari 7 prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Agenda Prioritas Ke-5 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar telah banyak dikontribusikan oleh peran strategis Kementerian PUPR.
Sejumlah pencapaian penting pembangunan infrastruktur telah diraih, seperti peningkatan akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan sanitasi, serta pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan transportasi yang memudahkan arus barang dan orang antarwilayah. Sebagian besar pembangunan infrastruktur terutama terkait pelayanan dasar serta konektivitas yang menjadi backbone yang telah terbangun saat ini banyak didukung oleh Kementerian PUPR. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah berperan penting dalam memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Salah satu contoh peran strategis Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur yang cukup masif yakni pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kami melihat dalam 2 tahun terakhir dukungan pembangunan infrastruktur yang dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR dalam menyiapkan infrastuktur dasar, perkantoran dan hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN sudah sangat maksimal dan sejalan dengan perencanaan yang telah disusun. Pembangunan infrastruktur strategis di IKN yaitu pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dapat dimanfaatkan untuk menjamin penyediaan air di kawasan tersebut.
Kemudian, masih terdapat tantangan pembangunan infrastruktur di daerah, terutama terkait dengan pemerataan akses infrastruktur, khususnya di daerah perbatasan maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang juga menjadi bagian dari isu strategis daerah. Jika kawasan yang terisolir tidak dibuka, maka sulit mewujudkan harapan untuk melakukan pemerataan pembangunan, dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan konektivitas menjadi sangat penting untuk dapat membuka kawasan yang terisolasi dan harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, sebagai contoh program food estate di Kalimantan Tengah, program hilirisasi industri berbasis mineral di Wilayah Sulawesi, serta program pembangunan sektor pariwisata di Wilayah Nusa Tenggara.
Seluruh program prioritas pemerintah tersebut masih menjadi agenda bersama pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan kewilayahan seperti infrastruktur yang menghubungkan simpul-simpul transportasi seperti jalan nasional yang menghubungkan terminal, pelabuhan dan bandara internasional. Melihat tantangannya yang cukup banyak, maka kami di Bappenas sangat membutuhkan dukungan, kolaborasi dan sinergi khususnya dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta unit organisasi terkait di Kementerian PUPR.
Bappenas bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyusun dokumen perencanaan jangka panjang yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, dengan visi “Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" yang sekaligus sebagai langkah strategis mencapai Visi Indonesia Emas 2045, mewakili cita-cita dan mimpi 100 tahun Indonesia merdeka. RPJPN 2025-2045 merupakan “haluan” yang menjadi pedoman arah pembangunan Indonesia dalam 20 tahun ke depan yang memerlukan orkestrasi upaya pembangunan dari seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun non pemerintah, agar sejalan, selaras, dan terpadu.
Sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045 dalam RPJPN, terdapat 5 sasaran utama Pembangunan tahun 2045, yang pertama adalah pencapaian pendapatan per kapita Indonesia setara negara maju. Untuk itu, jebakan middle income trap harus diatasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, minimal sebesar 6-7 persen per tahun. Sasaran kedua, tingkat kemiskinan menuju 0% dengan ketimpangan yang semakin berkurang baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah Timur dan Barat Indonesia. Sasaran ketiga, meningkatnya kepemimpinan Indonesia dan pengaruhnya di dunia internasional.
Kemudian, sasaran keempat yakni daya saing sumber daya manusia yang terus meningkat, serta kelima, intensitas emisi Gas Rumah Kaca yang menurun menuju Net Zero Emission. Sasaran yang cukup ambisius tersebut tentu saja harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti dengan sinergi yang kuat antar pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya, lintas wilayah dan lintas sektor.
Untuk mencapai berbagai target tersebut, maka dukungan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan pengolahan sampah sampai dengan saat ini tetap perlu memperoleh dukungan dalam pelaksanaan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 selanjutnya. Di sisi lain pembangunan infrastruktur, juga diutamakan dalam mendukung konektivitas untuk menghubungkan kawasan-kawasan yang dapat mendorong pertumbuhan seperti kawasan industri serta wilayah yang dapat menjadi pusat pertumbuhan baru.
Terkait Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) yang menjadi produk BPIW Kementerian PUPR, maka RPIW tersebut harus berpedoman pada RPJPN dan RPJMN. RPIW menurutnya dapat menjadi bridging atau menjembatani target-target Visi Indonesia 2045, yaitu menjembatani hal-hal yang bersifat makro menjadi yang sifatnya implementable atau program kegiatan yang dapat diterapkan unit organisasi terkait di Kementerian PUPR. Hal ini dicontohkan melalui ilustrasi rencana di sektor pertanian. Target swasembada pangan harus disinkronkan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan bendungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan kebutuhan dukungan konektivitas logistik pertanian yang dapat didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Selanjutnya sinkronisasi ini dapat dirumuskan melalui penyusunan RPIW yang lebih rinci mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPN dan RPJMN. Agar sasaran yang cukup ambisius tersebut dapat tercapai menurutnya perlu ada dukungan perumusan dan perencanaan program infrastruktur Kementerian PUPR.
Kami di Bappenas merumuskan strategi perencanaan pengembangan wilayah, dan kebutuhan dukungan pembangunan infrastruktur yang diterjemahkan ke dalam rencana pengembangan wilayah tentunya perlu ada peran dan kolaborasi bersama BPIW melalui penyusunan RPIW. Misalnya kawasan di Provinsi Kalimantan Tengah yang didorong menjadi sentra produksi pangan dan pusat konservasi internasional. Ketika sudah ditetapkan arah dan strategi kebijakannya, maka Kementerian PUPR dapat merumuskan infrastruktur yang dibutuhkan.
Contoh lain adalah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, yang merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan dukungan konektivitas untuk menghubungkan kawasan strategis sampai dengan pelabuhan atau simpul lainnya, maka disitulah fungsi RPIW sebagai acuan dalam memberikan arahan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memastikan perencanaan dan realisasi pengembangan konektivitas tersebut. Jadi intinya memastikan kebutuhan infrastruktur di suatu wilayah sejalan dengan prioritas RPJPN dan RPJMN.
Tentunya dalam merumuskan RPIW yang berpedoman kepada RPJPN dan RPJMN perlu dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Apresiasi terhadap pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) dan Konsultasi Regional (Konreg) oleh BPIW Kementerian PUPR dalam rangka perencanaan pembangunan infrastruktur untuk memastikan konsistensi antara rencana yang dituangkan di dalam RPJPN dan RPJMN dengan rencana pembangunan infrastruktur wilayah oleh Kementerian PUPR serta rencana Kementerian/Lembaga lainnya bahkan dengan rencana daerah. Perencanaan harus tersambung dan BPIW Kementerian PUPR perlu memastikan hal tersebut dalam penyusunan RPIW dalam aspek infrastruktur KePUPR-an.
Dalam konteks sinergi perencanaan kewilayahan, Bappenas memiliki harapan besar kepada BPIW Kementerian PUPR melalui RPIW dapat menterjemahkan Visi Indonesia Emas 2045 serta agenda jangka menengah pemerintahan saat ini. Disampaikan pula bahwa peran BPIW cukup selaras dengan peran Kedeputian Bidang Pengembangan Regional yang menerjemahkan visi besar ke dalam rencana pembangunan masing-masing wilayah. Disamping fungsi koordinasi dan perencanaan, menurutnya, BPIW nantinya melalui RPIW memiliki “dukungan lebih” atau “kewenangan lebih” untuk memastikan unit organisasi di Kementerian PUPR mengikuti rencana pembangunan yang disusun oleh BPIW yang merupakan penerjemahan dari RPJPN dan RPJMN. BPIW harus bisa mengarahkan unit organisasi di Kementerian PUPR agar sesuai dengan arahan pengembangan wilayah yang sudah disepakati, entah itu sifatnya budgeting atau sifatnya programming. Jadi kalau perencanaan infrastruktur belum dirumuskan BPIW melalui RPIW, maka baiknya unit organisasi lain tidak menjalankan untuk menjamin keselarasannya.
Terkait hal ini, BPIW punya kekuatan untuk bisa “mengarahkan” dalam pembangunan infrastruktur Ke-PUPR-an. Hal tersebut, apabila dikolaborasikan dengan tugas dan fungsi Bappenas yang berperan dalam memastikan seluruh program dan kegiatan di Kementerian/Lembaga sejalan dengan visi misi presiden dan wakil presiden, maka harapan pencapaian sasaran pembangunan akan lebih optimis dapat tercapai. BPIW harus memastikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif, efisien, serta sekaligus meningkatkan stok infrastruktur melalui dokumen RPIW.

Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dibuat Kementerian PPN/Bappenas terdapat Proyek Prioritas Nasional atau yang dikenal dengan nama Major Project, yang di dalamnya berisi kumpulan proyek yang memiliki daya ungkit tinggi dalam mencapai sasaran RPJMN.
Beberapa proyek yang memiliki kontribusi yang signifikan mendukung target RPJMN 2020 –2025 dan RPJPN 2005 – 2025 di Wilayah I, yaitu:
Menurut Abdul Malik Sadat Idris dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 dan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 di Wilayah I yakni Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali, memiliki beberapa isu strategis. Pulau Sumatera memilki beberapa isu strategis yakni belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan wilayah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Kemudian, belum optimalnya kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah ke bawah.
Isu strategis lainnya di Pulau Sumatera yakni degradasi lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena aktivitas perkebunan kelapa sawit, alih fungsi lahan, serta pertambangan. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar terutama fasilitas dan tenaga kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T juga menjadi isu strategis di Pulau Sumatera ini. Selain itu, di pulau ini masih terbatas kapasitas dan kualitas infrastruktur, khususnya konektivitas antarwilayah, infrastruktur ekonomi, infrastruktur dasar, dan lain-lain.
Tidak hanya itu, di Pulau Sumatera terdapat isu strategis berupa masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di pesisir barat; dan maraknya kriminalitas (narkoba, human trafficking) di daerah perbatasan negara. Beberapa isu strategis juga terdapat di Pulau Jawa dan Pulau Bali yakni masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah, karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara wilayah bagian Utara dan Selatan, serta wilayah kepulauan di Pulau Jawa dan Pulau Bali tersebut.
Isu strategis lainnya yakni masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa. Kemudian, isu strategis terkait degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
Pulau Jawa dan Pulau Bali juga memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur layanan dasar, konektivitas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor primer, industri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu ada isu strategis terkait belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya missmatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi Covid-19.
Isu strategis berikutnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali terkait pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat aktivitas ekonomi regional dan pusat pelayanan publik antara lain melalui pemenuhan infrastruktur perkotaan seperti layanan angkutan kota dan transportasi massal dan penataan kawasan, penataan permukiman kumuh, pemenuhan layanan dasar perkotaan dan amenitas perkotaan, serta peningkatan ketahanan bencana dan Kualitas lingkungan perkotaan.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian PUPR yang perlu disinkronkan untuk Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali antara lain pertama, Penyelarasan Prioritas Pembangunan Wilayah. Program-program yang tercantum di dalam Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) harus selaras dengan indikasi program yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, sasaran dan tujuan yang diidentifikasi dalam RPIW juga harus mampu mendukung dan memperkuat tujuan pembangunan jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam RPJMN.
Kedua, sinkronisasi terkait basis data dan informasi kewilayahan antara RPIW dan RPJMN. Kedua dokumen ini perlu menggunakan data dan analisis yang konsisten terkait kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di setiap wilayah. Konsistensi data ini memastikan bahwa dasar perencanaan yang digunakan akurat dan berbasis fakta yang sama.
Sinkronisasi yang ketiga yang sangat penting untuk dilakukan yakni mekanisme pembiayaan. Strategi pembiayaan yang diuraikan dalam RPIW harus selaras dengan alokasi anggaran yang direncanakan dalam RPJMN. Pendekatan pembiayaan multi-sumber yang disusun dalam RPIW perlu mencerminkan strategi keuangan yang dirancang dalam RPJMN untuk memastikan keberlanjutan pendanaan bagi proyek-proyek strategis.
Kemudian yang keempat, yakni sinkronisasi terkait target dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diusulkan dalam RPIW harus diselaraskan dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN. Indikator-indikator ini harus mampu mencerminkan hasil pembangunan yang terukur, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif.
Abdul Malik pun memberikan beberapa contoh sinkronisasi kebijakan yang perlu dilakukan Bappenas dengan Kementerian PUPR, yakni:
Kemudian, terkait perencanaan infrastruktur, Kementerian PUPR melalui BPIW menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) sesuai amanat Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR No. 817 tahun 2024 tentang RPIW.
Terkait kedudukan dalam kebijakan, RPIW mengacu pada RPJMN dan RPJPN. Kemudian RPIW menjadi input bagi pelaksanaan Rakorbangwil dan Konreg Kementerian PUPR yang pada akhirnya menjadi input terhadap rencana kerja Kementerian PUPR. Mengenai hal ini Abdul Malik mengatakan bahwa dirinya mendukung dengan hasil penyusunan RPIW akan menjadi referensi input usulan dalam forum-forum perencanaan dari pemerintah daerah.
Usulan tersebut dapat diusulkan dalam forum Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR, forum perencanaan lainnya seperti Rakortek – Rakorgub – Musrenbangprov dan pada akhirnya bermuara pada usulan Musrenbangnas RKP tiap tahun. Dikatakannya juga bahwa sesuai dengan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan terkait pelaksanaan Musrenbangnas RKP dan RKPD.
Terkait peran BPIW Kementerian PUPR melalui RPIW dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, Abdul Malik berharap BPIW mampu untuk menyusun perencanaan infrastruktur wilayah dalam RPIW yang terintegrasi dengan perencanaan kewilayahan, seperti RPJPN, RPJMN, RKP; perencanaan sektoral yang telah dilakukan juga di Kementerian PPN/Bappenas, serta kementerian lembaga lainnya (contoh: JUTPI, RITJ, RUPTL). “Hal ini agar dapat mendukung pengintegrasian infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan penguatan kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.
Perencanaan infrastruktur wilayah yang perlu untuk terus didasarkan pada karakteristik khas dan/atau fungsionalitas dari suatu kawasan, seperti kawasan perkotaan kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan sebagainya. Ia juga berharap BPIW juga mengupayakan perencanaan infrastruktur yang tidak hanya mendorong kemajuan wilayah, tetapi juga mendukung keberlanjutan dengan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian, alternatif pembiayaan juga perlu dimunculkan dalam perencanaa infrastruktur karena kapasitas fiskal daerah yang sebagian besar masih belum cukup. “Pengarusutamaan teknologi terbaru dalam pengembangan infrastruktur kewilayahan juga perlu dioptimalkan, baik dalam bidang konstruksi maupun energi,” pungkasnya.(**)

Industri yang berkelanjutan adalah jenis industri yang beroperasi dengan cara memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pada implementasinya, industri ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, mengurangi limbah dan emisi, serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara holistik. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Indonesia, menduduki posisi ke-2 setelah DKI Jakarta. Sektor Industri memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Jawa Timur yaitu sebesar 30,34% dari total PDRB di tahun 2023.
Dengan demikian menjadi tak terelakkan bahwa pertumbuhan sektor industri vital terhadap perkembangan Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, berkembangnya sektor industri juga memunculkan berbagai masalah terutama terkait lingkungan, seperti pencemaran lingkungan akibat kurang optimalnya pengelolaan sampah dan limbah, alih fungsi lahan, bencana banjir dan erosi, serta eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum berfungsi mendorong potensi pengembangan suatu wilayah, pada konteks Jawa Timur, infrastruktur PU berperan dalam meningkatkan konektivitas, penyediaan air bersih, dan mengelolaan sampah. Policy brief ini disusun dengan maksud untuk menjawab pertanyaan, apakah infrastruktur PU yang telah dibangun mampu mendorong pertumbuhan industri sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sehingga visi industri yang berkelanjutan di Jawa Timur dapat terwujud.
Pendahuluan
Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya atau yang sebelumnya disebut sebagai Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. WM Surabaya terdiri dari Kota Surabaya sebagai kota inti dan hinterlandnya yang meliputi Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Lamongan. Kota dan Kabupaten dalam WM ini saling terhubung secara ekonomi, sosial, dan transportasi. Dalam Perpres No. 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, tujuan penataan ruang Gerbangkertosusila adalah untuk menjadi pusat ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi sirkuler.
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan Ekspor ke Pasar Global. Industri pengolahan di Jawa Timur menyumbang sebesar 18,9% atau senilai Rp. 901,8 T dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional sektor industri, nilai ini merupakan yang terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat (23,03% atau Rp. 1.099 T) di tahun 2023. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional menetapkan 9 Kawasan Industri (KI) eksisting dan 6 KI rencana di Jawa Timur. 7 KI eksisting tersebut meliputi Surabaya Industrial Estate Rungkut di Kota Surabaya; Sidoarjo Industrial Estate Berbek dan Kawasan Industrial Safe N Lock di Kab. Sidoarjo; Maspion Industrial Estate, Java Integrated Industrial and Port Estate, dan Kawasan Industri Gresik di Kab. Gresik; dan Ngoro Industrial Park di Mojokerto. Adapun 4 KI rencana yaitu KI SiRIE di Kab. Sidoarjo, KI Salt Lake di Kab. Gresik, KI Maritim di Kab. Lamongan, dan Madura Industrial Seaport City di Kab. Bangkalan.
Dari jumlah tersebut 7 KI eksisting dan 4 KI rencana berada dalam WM Surabaya, sehingga bisa dikatakan WM Surabaya merupakan penopang sektor industri di Jawa Timur. Beberapa sektor industri utama di Surabaya meliputi manufaktur/industri pengolahan termasuk galangan kapal, alat-alat berat, pengolahan makanan, elektronik, dan perabotan rumah tangga. Beberapa perusahaan besar yang memiliki pabrik di WM Surabaya diantaranya PT Semen Indonesia, Maspion Group, Wings Group, Unilever Indonesia, PT. PAL Indonesia, dll.
Pendekatan
Bagaimana mengukur tingkat keberhasilan infrastruktur PU dalam mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan di WM Surabaya? Mengukur industri yang berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup 3 aspek utama: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada policy brief ini, hanya akan dibahas pada aspek yang terkait erat dengan Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum yaitu aspek lingkungan dan ekonomi. Pembahasan juga akan dikerucutkan pada sektor-sektor yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu konektivitas, penyediaan air baku industri, dan sanitasi.
A. Konektivitas
Identifikasi ruas-ruas jalan prioritas terhadap aktivitas industri di WM Surabaya dapat dilihat pada pergerakan lalu lintas (matriks asal dan tujuan). Berdasarkan matriks dibawah ditemui bahwa pergerakan tertinggi terjadi antara Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Pada Kab. Sidoarjo terdapat bandara Juanda, sedangkan pada Kab. Gresik dan Kota Surabaya terdapat Pelabuhan Utama Tanjung Perak dan Pelabuhan-pelabuhan industri. Pada ketiga Kab/Kota tersebut juga terdapat jumlah kawasan industri terbanyak.
Total panjang jalan nasional di GKS Plus adalah sebesar 606,61 km dengan lebar rata-rata 12,59 m. Dari segi kinerja, kemantapan jalan 98% (594,48 km), IRI rata-rata 4,92, dan VCR rata-rata 0,68. terdapat jalan dengan VCR>0,8 (LoS kategori D) sepanjang 162,8 km (26,84%) dan jalan dengan VCR>1 (LoS kategori E) sepanjang 160,74 (26,49%). Ruas-ruas jalan dengan VCR besar tersebut sudah membutuhkan penanganan strategis agar tidak terjadi kemacetan parah yang dapat mengurangi kinerja jalan.
Untuk mendukung konektivitas industri, WM Surabaya juga didukung dengan pembangunan ruas-ruas jalan tol. Berdasarkan Kepmen PUPR No. 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040, Jalan tol yang sudah beroperasi meliputi: Mojokerto-Surabaya (36,27 km), Krian-Legundi-Bunder (29 km), Surabaya-Gresik (20,7 km), Surabaya-Gempol (48,85 km), dan SS Waru-Bandara Juanda (12,8 km). Adapun jalan tol yang masih rencana meliputi: Krian-Pucukan (32 km), Bandara Juanda-Tj. Perak (23 km), dan Waru-Wonokromo-Tj. Perak (18,2 km). Pembangunan ruas-ruas jalan tol tersebut dimaksudkan untuk memisahkan pergerakan antara aktivitas logistik termasuk di dalamnya industri dengan aktivitas perkotaan, dengan demikian distribusi logistik antar kawasan industri dengan pelabuhan bisa dipercepat.
B. Air Baku Industri
Capaian akses air perpipaan di WM Surabaya mencapai 27,28%, dimana akses air perpipaan tertinggi berada di Kota Surabaya (96,81%) dan terendah berada di Kab. Lamongan (6,64%).
Pada skala regional, terdapat 2 SPAM Regional yaitu SPAM Umbulan dan SPAM Mojolagres. SPAM Umbulan adalah proyek dengan skema KPBU pertama untuk sektor air minum di Indonesia. SPAM Umbulan melayani 5 Kab/Kota yaitu: Kab. Sidoarjo (1200 lps), Kab. Gresik (1.000 lps), Kab. Pasuruan (410 lps), Kota Pasuruan (110 lps), Kota Surabaya (1.000 lps), dan PDAB Jawa Timur (280 lps). SPAM Umbulan memiliki kapasitas produksi 2.700 l/dtk masih dibawah kapasitas desain 4.000 l/dtk dikarenakan tidak tersedianya sumber air baku lagi.
SPAM Regional Mojolagres memanfaatkan sumber air yang berasal dari Sungai Brantas dengan kapasitas intake terpasang direncanakan sebesar 300 l/dt. Pembangunan unit pengolahan air bersih direncanakan terbagi ke dalam 3 tahap pengembangan dengan total kapasitas produksi sebesar 300 l/dt. Pembangunan tahap I SPAM pada tahun 2012 dengan kapasitas IPA sebesar 50 l/dt. Pembangunan tahap II tahun 2017 dengan penambahan kapasitas IPA 150 l/dt. Pada tahun 2026 direncanakan pembangunan SPAM lanjutan dengan pembiayaan diajukan dari loan. Penerima manfaat yang ditargetkan adalah sebanyak ±14.929 SR atau 400.000 jiwa di 3 Kab/Kota, Kab. Mojokerto 7.819 SR, Kab. Lamongan 1.177 SR, dan Kab. Gresik 5.933 SR.
Terdapat pula SPAM Karangbinangun dan SPAM Brondong yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dan termasuk dalam proyek strategis sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Selain itu, beberapa kabupaten/kota di Gerbangkertosusila juga mengembangkan SPAM lokal untuk memenuhi kebutuhan air baku industri dan domestik. Misalnya, Kabupaten Sidoarjo memanfaatkan sumber air dari Kalimati dan Kali Pelayaran untuk pelayanan di wilayah Sidoarjo Barat. Penyediaan air baku untuk industri di wilayah Gerbangkertosusila merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, PDAM setempat, dan SPAM regional maupun lokal. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air baku yang cukup bagi kebutuhan industri dan masyarakat.
C. Pengelolaan Sanitasi
Pengelolaan sanitasi yang menjadi kewenangan Kementerian PU mencakup pengelolaan limbah domestik, lumpur tinja, dan pengelolaan sampah. Pada prinsipnya, Kementerian PU bertanggung jawab pada pengelolaan sanitasi di kawasan permukiman dan bukan pada pengelolaan limbah di dalam Kawasan Industri. Beberapa peraturan seperti Permen Lingkungan Hidup No.3/2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Kawasan Industri, PP No. 142/2015 tentang Kawasan Industri, dan PP No. 22/2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa Kawasan Industri wajib mengelola limbahnya sendiri melalui fasilitas pengolahan yang memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Permen PUPR No.4/2017 menyatakan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha dapat dibangunkan SPALD-T, sedangkan untuk kawasan strategis berkepadatan penduduk <150 jiwa/ha dapat dibangunkan SPALD-S. Kepadatan penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota pada WM Surabaya adalah sebagai berikut: Kota Surabaya (85,85 jiwa/Ha), Kab. Gresik (10,89 jiwa/Ha), Kab. Bangkalan (10,31 jiwa/Ha), Kab. Mojokerto (15,96 jiwa/Ha), Kota Mojokerto (69,93 jiwa/Ha), Kab. Sidoarjo (30,82 jiwa/Ha), dan Kab. Lamongan (7,76 jiwa/Ha). Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Surabaya, diikuti dengan Kota Mojokerto, dan Kab. Sidoarjo. Namun demikian, berdasarkan angka tersebut, jika dilihat dalam skala kota/kab, belum ada kota/kab di WM Surabaya yang sudah memenuhi kriteria pembangunan SPALD-T. Analisis yang dihasilkan mungkin berbeda jika perhitungan dilakukan pada skala kecamatan.
Terkait pengolahan lumpur tinja, terdapat 4 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di WM Surabaya, yaitu: IPLT Keputih di Kota Surabaya, IPLT Betoyoguci di Kab. Gresik, IPLT Sidokumpul di Kab. Lamongan, dan IPLT Griyomulyo Jabon di Kab. Sidoarjo. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum memiliki IPLT yaitu, Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Mojokerto. Pada pelayanan persampahan, seluruh Kab/Kota telah memiliki Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masing-masing. Namun demikian, berdasarkan analisis kapasitas dan timbunan sampah/tahun didapati bahwa hampir seluruh TPA di WM Surabaya dalam kondisi overload, hanya terdapat 1 TPA yaitu TPA Benowo di Kota Surabaya yang masih memiliki umur layanan hingga 3 tahun lagi. Untuk memenuhi kebutuhan hingga 5 tahun ke depan masih dibutuhkan program-program peningkatan layanan persampahan berupa pembangunan TPST, TPS3R, perluasan landfill, hingga pembangunan instalasi RDF.
Hasil
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki tugas merumuskan kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah secara terpadu dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II telah melaksanakan kajian penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila (WM Surabaya). Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam perencanaan infrastruktur wilayah metropolitan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah khususnya sektor industri serta sebagai masukan dalam pembaruan dokumen RPIW Provinsi Jawa Timur khususnya pada Bab VIII Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur.
Dalam membuat perencanaan WM Surabaya dengan tujuan akhir peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, perencanaan dimulai dari mengindentifikasi isu dan permasalahan, menganalisis kinerja infrastruktur terbangun dan menghitung gap kebutuhan infrastruktur sehingga kemudian dihasilkan rencana aksi pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah.
Permasalahan
• Hub transportasi khususnya Pelabuhan belum maksimal mendukung arus logistic di WM Surabaya
• Masih dibutuhkan peningkatan konektivitas antara WM Surabaya dengan hinterland dan pusat-pusat pertumbuhan lain di Jawa Timur untuk menjamin pemerataan
• Tingginya kebutuhan air baku dikarenakan besarnya jumlah penduduk di WM Surabaya serta aktivitas industri yang juga menuntut ketersediaan tampungan air baku permukaan dalam jumlah yang besar
• Masih rendahnya capaian akses air minum perpipaan di WM Surabaya.
• Tingginya tingkat pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri khususnya di Kab. Gresik dan Kab. Sidoarjo
• Tingginya alih fungsi lahan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan pertumbuhan industri yang pesat di WM Surabaya.
Rekomendasi Kebijakan
• Saat ini konektivitas antar Kawasan Industri (KI) di WM Surabaya dan antara KI dengan hub transportasi berupa bandara dan pelabuhan sudah terhubung dengan cukup baik melalui jaringan jalan tol. Namun demikian, masih dibutuhkan peningkatan kapasitas hub transportasi khususnya pelabuhan untuk mendukung arus logistik dari dan keluar kawasan menuju wilayah-wilayah lain di Indonesia.
• Untuk mendukung pemerataan logistik antara WM Surabaya dengan wilayah lain di Jawa Timur, masih dibutuhkan penuntasan tol Probolinggo-Banyuwangi dan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa beserta sirip-siripnya.
• Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum baik untuk industri maupun Kawasan permukiman di WM Surabaya, masih dibutuhkan pembangunan SPAM Regional Pantura salah satu proyek dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. SPAM ini akan melayani wilayah Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Lamongan dengan total layanan sebesar 166.000 SR.
• Selain itu, untuk meningkatkan capaian air minum perpipaan di WM Surabaya dibutuhkan pemenuhan RC oleh pemda dan PDAM.
• Untuk mendukung pelayanan persampahan, dibutuhkan pembangunan TPST baru dengan konsep 3R, untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan nilai ekonomi dari sampah daur ulang.
• Selain itu, untuk meningkatkan nilai ekonomi dari pengolahan sampah dibutuhkan dukungan pembangunan instalasi Refuse Derived Fuel (RDF) yang dapat mengubah sampah padat menjadi bahan bakar alternatif.
• Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan kegiatan penyusunan kajian Pengembangan WM Surabaya dengan fokus perencanaan sektor industri pengolahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
• Hasil kajian akan menjadi dasar dalam pembahasan program kegiatan pada forum-forum perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan, seperti Musrenbangnas, Rakortekrenbang, Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil), dan Konsultasi Regional (Konreg).
• Dibutuhkan revisi dokumen RPIW Provinsi Jawa Timur yang menyesuaikan dengan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan khususnya pada bab skenario pengembangan dan rencana aksi.
• BPIW melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain serta pemerintah daerah untuk merumuskan langkah-langkah komitmen pengembangan industri di WM Surabaya dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Kesimpulan
Pesatnya pertumbuhan Industri di WM Surabaya memberikan dampak ekonomi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini harus didukung dengan pertumbuhan infrastruktur yang memadai agar dampak negatif dari industri seperti meningkatnya kemacetan, limbah, dan pencemaran lingkungan dapat ditanggulangi dengan baik. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, efisiensi sumber daya dan distribusi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga manfaat pertumbuhan industri dapat dirasakan masyarakat luas.
BPIW diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap RPIW Kawasan Prioritas WM Surabaya yang telah disusun, hal ini untuk mendapatkan masukan revisi RPIW Jawa Timur khususnya pada bab rencana aksi. Revisi RPIW akan menjadi dasar dalam penetapan program tahunan pada forum-forum perencanaan seperti Rakorbangwil dan Koreg yang dilaksanakan setiap tahun. Selanjutnya, dokumen RPIW KP WM Surabaya akan menjadi masukan dalam RPJMD, RISPAM, masterplan air limbah dan masterplan persampahan WM Surabaya.(**)
Referensi/Rujukan
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan
3. Peraturan Menteri PUPR No. 17/PRT/M/2019 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW)
4. Keputusan Menteri PUPR No. 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040
5. PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (BPS)

Urgensi Infrastruktur dalam Pembangunan Nasional
Infrastruktur merupakan fondasi vital bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kehidupan sebuah negara. Infrastruktur berperan penting dalam mendukung aktivitas penduduk yang berkolerasi dengan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap sektor-sektor perekonomian seperti pertanian, industri, dan pariwisata yang akan berkembang dengan lebih optimal dengan dukungan infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun secara sinergis akan meningkatkan daya saing suatu negara melalui aksesibilitas, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta konektivitas antarwilayah yang memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Bagaimana tidak? Infrastruktur air baku, jalan, air bersih, sanitasi, dan perumahan merupakan elemen-elemen dasar yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara nyata bila infrastruktur tersebut berfungsi optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lalu kemudian, bagaimana dengan infrastruktur PUPR yang telah dibangun, apakah telah sesuai dengan tujuannya, membawa manfaat bagi masyarakat dan wilayah sekitar?
Berbeda dengan evaluasi terhadap infrastruktur PUPR yang rutin dilakukan, Evaluasi Manfaat Infrastruktur PUPR terbangun yang dilakukan oleh BPIW adalah untuk memastikan keberfungsian dan kebermanfaatan infrastruktur PUPR tersebut melalui beberapa tahapan. Tahap pertama dilakukan pengumpulan data rencana teknis berupa dokumen Feasibility Study (FS), Rencana Induk, atau rencana teknis lainnya yang menunjukkan kebermanfaatan dari infrastruktur yang direncanakan. Dokumen-dokumen rencana tersebut menjadi salah satu pedoman dalam melihat realisasi di lapangan. Kemudian, dilakukan survei lapangan dengan mengobservasi keseluruhan sistem infrastruktur secara fisik melalui beberapa parameter kesesuaian seperti lokasi, waktu, biaya, volume, area layanan/manfaat, serta perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya infrastruktur PUPR terhadap kondisi masyarakat dan wilayah sekitar. Yang menjadi poin penting adalah kegiatan evaluasi manfaat ini tidak bertujuan mencari kesalahan perencanaan maupun pelaksanaan suatu program/proyek, namun lebih untuk mengidentifikasi keberfungsian dan kebermanfaatan infrastruktur PUPR sebagai masukan program OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi) pada tahun ini maupun yang akan datang.
Kegiatan Evaluasi Manfaat Infrastruktur PUPR
BPIW telah 2 tahun berturut-turut melakukan kegiatan evaluasi manfaat infrastruktur PUPR, yaitu pada tahun 2023 dan 2024. Di tahun 2023, objek infrastruktur yang disurvei sebanyak 169 infrastruktur PUPR di seluruh provinsi. Sedangkan pada tahun 2024, evaluasi manfaat infrastruktur PUPR dilakukan terhadap 73 objek infrastruktur PUPR yang tersebar di 20 provinsi. Selain infrastruktur PUPR secara umum, infrastruktur PUPR yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga termasuk yang dievaluasi keberfungsian dan kebermanfaatannya.
Beberapa showcase evaluasi manfaat infrastruktur PUPR berikut setidaknya memberi gambaran umum keberfungsian dan kebermanfaatan infrastruktur PUPR.
Bendungan Tapin, Kalimantan Selatan
Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan merupakan upaya mewujudkan ketahanan pangan dan air nasional dengan luas wilayah mencapai 2.174,95 km2 dengan target luasan irigasi 5.472 ha. Bendungan ini mempunyai kapasitas tampung sebesar 50,26 juta m3 sesuai dengan yang direncanakan, sehingga target area manfaat terpenuhi dan meningkatkan indeks pertanaman dari 1,5 menjadi 2.
Selain sebagai penyedia air baku, Bendungan Tapin juga berfungsi sebagai pereduksi banjir yang terjadi di kawasan sekitarnya, khususnya di Kota Rantau, Ibu Kota Kab. Tapin. Bendungan ini mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata agar mendongkrak perekonomian wilayah tersebut. Selain itu, Bendungan Tapin juga berpotensi sebagai pembangkit listrik namun belum terutilisasi.
Terowongan Air Nanjung, Jawa Barat
Terowongan Air Nanjung berlokasi di hulu Sungai Citarum, tepatnya di Kel. Lagadar, Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Jawa Barat. Fungsi dibangunnya terowongan ini untuk memperlancar aliran Sungai Citarum ke hilir sehingga mereduksi banjir di kawasan Bandung Selatan yang sebelumnya kerap terjadi. Luasan banjir yang dapat tereduksi dari adanya terowongan ini mencapai 700 ha, dengan penurunan debit banjir sebesar 44,28 m3 /det. Manfaat nyata dari terowongan ini dirasakan oleh 14.000 KK yang terbebas dari banjir di kawasan tersebut.
SPAM Semarang Barat, Jawa Tengah
SPAM Semarang Barat dibangun di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah yang memanfaatkan sumber air dari Waduk Jatibarang dengan kapasitas intake terpasang sebesar 1.050 l/det sesuai dengan yang direncanakan. Untuk pembangunan unit pengolahan air bersih telah mencapai kapasitas produksi 624,29 l/det dan akan dituntaskan hingga mencapai target 1000 l/ det pada akhir tahun 2024.
Pembangunan SPAM ini berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan volume ketersediaan air yang layak konsumsi bagi masyarakat khususnya di Kec. Ngaliyan, Kec. Tugu, dan Kota Semarang Barat. Kebutuhan harian air bersih masyarakat terpenuhi, baik secara kuantitas maupun kualitas dengan adanya SPAM ini. Sebelumnya, masyarakat penerima manfaat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan airnya karena terbatasnya ketersediaan air bersih, sangat bergantung pada air tanah dan sumur bor. Keadaan ini membuat ketidaknyamanan terutama pada periode kemarau sehingga berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup. SPAM Semarang Barat menyediakan akses layanan air bersih 24 jam penuh agar masyarakat dapat menikmati air bersih tanpa gangguan atau ketidakpastian pasokan air sehari-hari. Dengan dibangunnya SPAM ini diharapkan masyarakat mengurangi aktivitas pengambilan air tanah sehingga risiko penurunan muka tanah dan kerusakan lingkungan dapat dikendalikan.
Jalan Tol Sigli-Banda Aceh
Jalan tol Sigli – Banda Aceh dibangun secara bertahap, sejak tahun 2020 hingga 2024 dengan panjang 74,19 km. Hingga saat ini, telah terdapat 5 seksi jalan tol yang beroperasi, yaitu jalan tol Seulimeum-Jantho, Jantho-Indrapuri, Indrapuri-Blang Bintang, Blang Bintang-Kuto Baro, dan Kuto Baro-Baitussalam. Untuk seksi Padang Tiji-Seulimeum terutama menuju ke Medan masih dalam tahap konstruksi dengan target selesai dan beroperasi di bulan September 2024. Bila ruas jalan tersebut selesai dengan perkiraan target operasional pada Desember 2024, maka perjalanan menuju Medan akan ditempuh dalam 9 jam dari 12 jam bila melalui jalan nasional. Sebelum dibangunnya jalan tol Sigli-Banda Aceh, pergerakan logistik sangat padat melalui jalan nasional dengan kecepatan rata-rata tergolong rendah akibat melewati permukiman penduduk sehingga waktu tempuh lebih lama. Disamping itu, jalan nasional di Kota Banda Aceh sering mengalami kemacetan, terutama di wilayah perkotaan, sehingga mempengaruhi mobilitas harian dan distribusi logistik. Waktu tempuh yang lama ini dirasakan oleh para pekerja dimana banyak pekerja yang tinggal di Kota Banda Aceh memerlukan waktu hingga satu jam untuk mencapai pusat perkantoran di Jantho. Sedangkan waktu tempuh dari Sigli menuju Banda Aceh melalui jalan non tol berkisar antara 2 hingga 2,5 jam.
Kondisi ini telah berubah sejak dibangunnya jalan tol Sigli-Banda Aceh yang mengurangi waktu tempuh sangat signifikan. Para pekerja hanya membutuhkan waktu 15 menit dari Banda Aceh menuju kawasan perkantoran di Jantho. Setelah tol beroperasi penuh, perjalanan dari Sigli menuju Banda Aceh ditempuh dalam 1-1,5 jam dan kepadatan jalan nasional menjadi berkurang, karena sebagian pengguna jalan beralih ke jalan tol terutama truk-truk pembawa barang, sehingga distribusi logistik tidak mengalami hambatan yang berarti.
Lima seksi Jalan tol Sigli-Banda Aceh yang telah beroperasi ini menyediakan akses yang lebih mudah menuju pusat-pusat perekonomian dan pengembangan wilayah, diantaranya akses menuju Pelabuhan Malahayati, Bandara Sultan Iskandar Muda, pusat pergudangan industri, pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar, dan kawasan wisata Lembah Seulawah. Namun demikian, sebagian pengguna jalan merasa biaya tol cukup tinggi sehingga pengguna memilih jalan nasional sebagai akses ke berbagai tujuan, terutama ke arah Bandara Sultan Iskandar Muda yang masih cukup jauh dari pintu keluar tol Blang Bintang karena tetap melalui jalan nasional menuju bandara tersebut.
Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)
Untuk level kawasan, KITB menjadi salah satu kawasan dengan PSN yang cukup lengkap, diantaranya drainase utama, TPST, IPA, IPAL, perumahan, dan jalan kawasan.
Drainase utama KITB yang dibangun pada tahun 2021 bertujuan untuk mengendalikan luapan air dikarenakan seringnya terjadi banjir pada Desa Celong yang terletak di hilir saluran drainase eksisting. Kapasitas drainase eksisting tersebut tidak dapat menampung aliran air yang turun cukup masif karena ketinggian antara KITB dan Desa Celong mencapai 40 meter. Dengan dibangunnya drainase tersebut, banjir tidak terjadi lagi. Setelah beberapa tahun drainase tersebut beroperasi, terjadi sedimentasi yang mempengaruhi kelancaran air, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan sedimentasi lebih sering agar laju air tidak tersendat dan mempengaruhi kinerja drainase tersebut.
Sedangkan di sektor jalan, jalan kawasan dibangun sepanjang 50,62 km dan jembatan 719 m yang berfungsi menghubungkan kantor pengelola, tenant, dan warga di dalam kawasan ke jalan tol dan jalan Pantura. KITB juga telah dilengkapi dengan infrastruktur Cipta Karya seperti TPST, IPA, dan IPAL yang secara umum telah berfungsi dan termanfaatkan dengan baik walaupun belum optimal. Ketidakoptimalan infrastruktur tersebut terjadi karena belum seluruh tenant di KIT Batang beroperasi.
Sebelum Instalasi Pengolahan Air (IPA) di KITB dioperasionalkan, jumlah tenant yang berinvestasi di kawasan ini masih relatif terbatas. Namun, setelah IPA KITB mulai beroperasi, terjadi peningkatan dalam jumlah tenant yang berinvestasi di kawasan tersebut. Ketersediaan infrastruktur air yang andal memberikan jaminan kepada calon investor bahwa kebutuhan dasar mereka akan terpenuhi dengan baik, sehingga mengurangi risiko operasional. Hal ini secara langsung mendorong pertumbuhan minat investasi dan penambahan tenant yang ingin mendirikan fasilitas industri di KITB.
IPA KITB memberikan manfaat besar bagi para tenant yang menempati kawasan tersebut. Saat ini, terdapat 14 tenant di KITB dan sekitar 42,85% sudah tercatat memanfaatkan infrastruktur air dari IPA KITB, diantaranya KCC Glass, Samator, Unipax Plasindo, Rumah Keramik Indonesia, Yih Quan, dan Wavin. Infrastruktur dasar seperti rusun, gedung pengelola, IPAL, TPST, dan tenant BPSP juga turut menunjang kegiatan operasional para tenant. Pembangunan ini tidak hanya menyediakan fasilitas untuk produksi, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi operasional dengan memberikan akses pada sistem pengolahan limbah, penyediaan air bersih, dan pengelolaan lingkungan secara terintegrasi.
Untuk mendukung pengoptimalan manfaat dari infrastruktur yang telah dibangun tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pihak pengelola KITB harus terus berupaya mempromosikan kawasan industri ini kepada para investor, baik di dalam negeri maupun internasional. Meskipun infrastruktur dasar telah tersedia, keberhasilan kawasan industri ini tetap bergantung pada sejauh mana minat investasi bisa ditingkatkan.
Upaya mempromosikan keunggulan KITB diantaranya ketersediaan infrastruktur yang memadai, dukungan pemerintah yang kuat, dan potensi keuntungan jangka panjang bagi investor perlu terus digencarkan. Dengan strategi promosi yang efektif, KITB dapat menarik lebih banyak perusahaan untuk menanamkan modal, yang bermuara pada percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut serta di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan.
Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 km merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera, dibangun sejak tahun 2017 dan selesai tahun 2020 dengan biaya mencapai Rp12,18 triliun. Jalan tol ini telah diresmikan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo pada 25 September 2020 lalu. Jalan Tol Pekanbaru - Dumai menghubungkan berbagai koridor ekonomi utama di Provinsi Riau, yaitu seperti Dumai-Duri-Kandis-Petapahan-Minas-Pekanbaru. Keberadaan jalan tol ini diharapkan meningkatkan dan memudahkan akses Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus kota bisnis dan Kota Dumai yang merupakan kota dengan industri perminyakan dan agribisnis yang potensial sebagai kota pelabuhan yang berada pada posisi lintas perdagangan internasional Selat Melaka. Terdapat lima kawasan industri di sana, yakni Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, Kawasan Pengembang Pelabuhan Terpadu (KPPT), Kawasan Pelabuhan (Pelindo I) dan Kawasan Industri Pengolahan Migas (Pertamina Reg II dan Chevron). Keberadaan jalan tol ini akan mengintegrasikan konektivitas kawasan, memperlancar arus distribusi barang dari pusat industri ke berbagai wilayah di Sumatera.
Dari sisi efisiensi, Jalan Tol Pekanbaru -Dumai dengan panjang 131,48 km sebagai jalan alternatif menuju Kota Pekanbaru dan Dumai merupakan pilihan rute yang lebih nyaman dan efisien dalam waktu tempuh karena mampu memangkas waktu perjalanan 2-3 jam jika dibandingkan melalui jalan nasional yang memerlukan waktu 5-6 jam perjalanan. Selain itu jalan tol ini memperpendek jarak tempuh sebesar 70 km dibandingkan melaui jalan nasional yang mencapai panjang 200 km. Terlebih jalan tol ini dilengkapi dengan TempatIstirahat dan Pelayanan (TIP). Terdapat sepuluh TIP dengan jarak antara masing-masing TIP sekitar 20 hingga 30 kilometer. Lima TIP terletak pada jalurA (Jalur Pekanbaru-Dumai) dan jalurB (Jalur Dumai-Pekanbaru) yakni di km 14+500 A&B, km 45+200 A, km STA 46+050 B, km 65+000 A&B, km 82+300 A&B, dan km 15+200 A&Bdari arah Dumai. TIP ini mulai dikerjakan pada tahun 2023, dan hingga saat ini, baru rest area km 45 yang telah berfungsi secara menyeluruh.
Jalan tol Pekanbaru-Dumai melintasi kawasan konservasi habitat gajah di Minas Kabupaten Siak dan Suaka Margasatwa Balai Raja yang mana kedua kawasan ini merupakan tempat perlintasan aktif gajah-gajah Sumatra di Provinsi Riau. Yang menarik dari jalan tol ini adalah adanya jembatan dan underpass yang dikhususkan untuk perlintasan satwa terutama gajah Sumatera, artinya pembangunan jalan tol ini memperhatikan keberlangsungan satwa sebagai unsur dari keanekaragaman hayati di Sumatera khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Perlintasan khusus satwa ini berlokasi di Seksi 2 antara Minas-Petapahan di Sungai Tekuana dan tidak jauh dari Pusat Latihan Gajah Minas, dan di Seksi 4 dekat dengan Suaka Margasatwa Balai Raja. Di kawasan Seksi 2 terdapat sedikitnya 13 gajah sumatera liar, dan di Seksi 4 antara Kandis Utara dan Duri Selatan terdapat dua kawasan suaka margasatwa, yaitu Balai Raja dan Giam Siak Kecia-Bukit Batu dengan populasi fauna antara lain gajah sumatera, harimau sumatera, beruang madu, dan tapir. Terowongan gajah dengan tinggi 5,1 m dan lebar 40 m telah disesuaikan dengan habitat aslinya di alam sehingga satwa tidak merasa asing di area jalan tol tersebut.
Pada bagian kiri dan kanan pada terowongan gajah dilengkapi dengan pagar pengaman agar satwa-satwa tersebut aman dan ekosistem tetap terjaga. Terowongan perlintasan gajah ini dibuat sekaligus untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan tol, agar tidak bersinggungan langsung dengan gajah yang melintasi area tersebut.
Konklusi
Kegiatan evaluasi manfaat infrastruktur PUPR yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya penjaminan berfungsinya dan bermanfaatnya infrastruktur yang dibangun bagi para pengguna atau penerima manfaat. Dari hasil evaluasi tersebut diketahui beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain dari aspek tata kelola dan kelembagaan. Perlunya kesiapan Pemerintah Daerah dalam melanjutkan infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat, sehingga manfaat infrastruktur dirasakan masyarakat secara langsung dan berkontribusi lebih jauh lagi terhadap pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian. Disamping itu, hasil evaluasi manfaat infrastruktur PUPR berperan dalam perbaikan perencanaan kedepan, sehingga infrastruktur yang direncanakan tidak hanya sebatas output namun diperlukan aspek pendukung lain baik fisik maupun non fisik yang signifikan mempengaruhi kebermanfaatan dan keberlanjutan infrastruktur terbangun. Selain itu, perencanaan yang mengusung pembangunan berbasis wilayah yang berkelanjutan telah dilakukan pada beberapa PSN tersebut dan merupakan langkah awal yang sangat baik bagi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan skala nasional.(**)

Secara global, imbas parah dari manifestasi krisis iklim sudah semakin destruktif dan meluas dirasakan di berbagai belahan dunia. Meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian bencana, seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan banjir, nyatanya telah banyak menelan korban jiwa, mengganggu stabilitas perekonomian, serta bahkan menghambat kemajuan pembangunan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Berdasarkan temuan dalam laporan yang disusun oleh UNOPS (2021), infrastruktur berkontribusi sebesar 79% dari total emisi GRK, serta 88% dari total biaya adaptasi perubahan iklim. Lebih lanjut, infrastruktur juga dinilai dapat mempengaruhi capaian keseluruhan 17 target SDGs sebesar 92%, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, data-data statistik tersebut memberikan seruan untuk menempatkan sektor infrastruktur sebagai sektor prioritas untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan.
Komitmen Indonesia dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
Setelah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia terus berupaya memutakhirkan kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku national focal point Indonesia untuk UNFCCC telah beberapa kali mengkomunikasikan dokumen NDC (Nationally Determined Contributions) Indonesia kepada UNFCCC. Terkini, melalui dokumen Enhanced NDC Indonesia pada bulan September 2022 yang lalu, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi GRK di tahun 2030 dari sebesar 29% menjadi 31,89% dengan kemampuan sendiri. Jika dengan dukungan internasional, targetnya dinaikkan dari sebesar 41% menjadi 43,2%, pada sektor-sektor mitigasi bidang: (i) Energi (15.5%); (ii) Limbah (1.5%); (iii) Industri (0.3%); (iv) Pertanian (0.4%); serta (v) Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (25.4%). Pemutakhiran target tersebut didasarkan pada perkembangan kebijakan nasional dan sektoral terkait penanganan perubahan iklim, salah satunya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang di dalamnya juga mengatur tentang pasar karbon. Perpres NEK ini menandai langkah awal Indonesia dalam berkontribusi untuk penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar (market) yang diharapkan dapat menggerakkan lebih banyak lagi pembiayaan dan investasi hijau yang tentunya dapat berdampak pada pengurangan emisi GRK. Selain itu, telah disusun pula dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) yang memuat arahan jangka panjang untuk implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menuju target net-zero emissions Indonesia 2060 atau lebih cepat, beserta komitmen NDC per 5 (lima) tahunan selanjutnya.
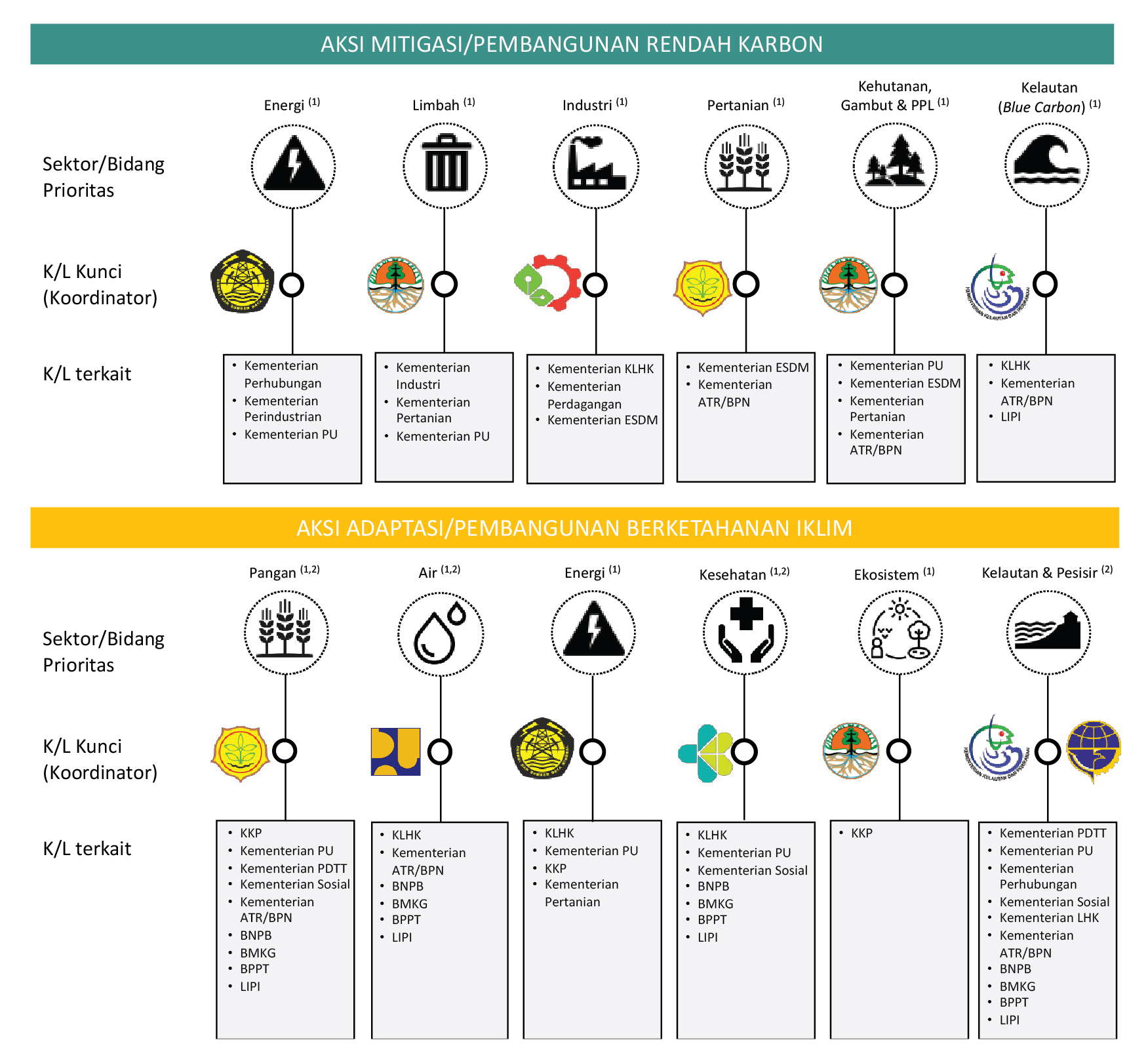
Sebagai upaya memastikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim betul-betul dilakukan secara terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional, Kementerian PPN/ Bappenas mengintegrasikan konsep Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dengan menjadikan target penurunan intensitas emisi GRK menuju net-zero emissions sebagai salah satu sasaran utama untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebanyak 93,5 persen hingga tahun 2045. Lebih lanjut, dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu sasaran utama dalam Prioritas Nasional ke-8, dengan target berupa penurunan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB, serta penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan & pesisir, air, pertanian, dan Kesehatan).
Dengan telah diintegrasikannya komitmen Indonesia untuk makin berkontribusi dalam menjaga suhu global dan ketahanan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan sektoral dituntut untuk lebih berorientasi pada pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim, dan berkelanjutan, termasuk sektor infrastruktur PU.
Dalam konstelasi kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim tersebut, terdapat beberapa bidang/sektor prioritas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia yang membutuhkan dukungan dan kontribusi Kementerian PU (Lihat Gambar 1). Untuk upaya mitigasi perubahan iklim, dukungan dan kontribusi Kementerian PU diperlukan pada 3 (tiga) sektor/bidang prioritas, yaitu: energi; limbah; serta kehutanan, gambut, dan perubahan penggunaan lahan. Sedangkan, untuk adaptasi perubahan iklim, Kementerian PU berperan sebagai K/L kunci pada sektor air, serta turut berkontribusi pada sektor/bidang prioritas: pangan, energi, kesehatan, serta kelautan & pesisir. Melihat begitu besarnya peran infrastruktur PU dalam upaya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, sepertinya tidak ada alasan lagi bagi Kementerian PUPR untuk tidak memberikan dukungan dan kontribusi aksi iklim yang lebih ambisius, terutama pada sektor/bidang prioritas air.
Kiprah Kementerian PU dalam Aksi Iklim
Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam merespon isu perubahan iklim, Kementerian PU telah berupaya untuk ikut berkontribusi dalam upaya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Untuk mengadopsi prinsip pembangunan infrastruktur berkelanjutan, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman penyelenggataan Konstruksi Berkelanjutan. Terkait pembangunan gedung hijau (green building), penerapan pembangunan infrasturuktur PU telah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.
Beberapa contoh penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk infrastruktur PU dalam mendukung upaya pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim antara lain:
• Sektor Sumber Daya Air
• Sektor Jalan
Konektivitas Jalan Tol memiliki manfaat besar khususnya dalam peningkatan perekonomian, sehingga perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan berkelanjutan sejak tahap perancangan, pembangunan, pengoperasian, hingga tahap pemeliharaan. Melalui proses sertifikasi Green Toll Road Indonesia yang dilakukan oleh Green Infrastucture and Facilities Indonesia, Jalan Tol Gempol - Pandaan dan Jalan Tol Pandaan – Malang mendapatkan sertifikat Green Toll Road Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jalan tol, Kementerian PU setiap tahunnya melakukan penilaian terhadap kualitas layanan di seluruh ruas jalan tol, berdasarkan 3 (tiga) aspek penilaian jalan tol berkelanjutan yaitu: fungsi utama jalan tol, fungsi pendukung di rest area, serta fungsi pelengkap di rest area sebagaimana tertuang dalam Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2014 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dan Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol.
• Sektor Permukiman
Rekomendasi Pengarusutamaan Aksi Iklim dalam Perencanaan Infrastruktur PU Jangka Menengah 2025-2029
Sebagai upaya implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tertuang dalam RPJPN 2025-245 dan RPJMN 2025-2029, pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan infrastruktur PU dapat dilakukan melalui pendekatan co-benefits. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat berperan mengubah konstelasi perencanaan untuk suatu pembangunan infrastruktur rendah karbon dan berketahanan iklim karena memiliki dua atau lebih manfaat kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung. Pemahaman mengenai co-benefits juga dapat mendorong sinergitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau desain infrastruktur rendah karbon dan berketahanan iklim yang lebih integratif. Selain itu dari sisi masyarakat, mengakumulasikan co-benefits juga dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan perubahan iklim ketika dapat memberikan manfaat tambahan yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan hidupnya sehari-hari. Rekomendasi pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan infrastruktur PU jangka menengah 2025-2029 dijabarkan dalam matriks berikut:
Rekomendasi Pengarusutamaan Aksi Iklim untuk Infrastruktur PU
Sebagai upaya implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tertuang dalam RPJPN 2025-245 dan RPJMN 2025-2029, pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan infrastruktur PU dapat dilakukan melalui pendekatan co-benefits. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat berperan mengubah konstelasi perencanaan untuk suatu pembangunan infrastruktur rendah karbon dan berketahanan iklim karena memiliki dua atau lebih manfaat kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung.
Pemahaman mengenai co-benefits juga dapat mendorong sinergitas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau desain infrastruktur rendah karbon dan berketahanan iklim yang lebih integratif. Selain itu dari sisi masyarakat, mengakumulasikan co-benefits juga dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan perubahan iklim ketika dapat memberikan manfaat tambahan yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan hidupnya sehari-hari. Rekomendasi pengarusutamaan aksi iklim dalam perencanaan infrastruktur PU jangka menengah 2025-2029 dijabarkan dalam matriks di samping:
Penutup
Pembangunan infrastruktur PU memegang peranan yang sangat penting untuk melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya, sekaligus mencegah terus meningkatnya produksi emisi GRK penyebab pemanasan global. Transformasi pembangunan infrastruktur PUPR yang rendah karbon tengah diupayakan melalui penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan dan penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau yang telah diwujudkan pada sejumlah proyek-proyek percontohan (pilot projects) seperti pembangunan Gedung Kantor Kementerian PUPR, pasar tradisional, serta rumah susun hemat energi. Namun, upaya transformasi pembangunan infrastruktur PU ini juga harus dipastikan tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang sudah tak terelakkan lagi dengan frekuensi dan intensitas yang semakin meningkat dan destruktif.
Untuk itu, skenario perencanaan infrastruktur PU jangka menengah 2025-2029 bukan hanya untuk menjawab layanan infrastruktur PU apa yang diperlukan di suatu kawasan/wilayah perencanaan, namun lebih pada bagaimana menyediakan infrastruktur PU secara tangguh, berkelanjutan, dan kompatibel dengan masa depan yang bebas karbon. Jangan lagi melakukan perencanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur PU yang ‘business as usual’ tanpa memikirkan keterkaitan dampak dan pengaruhnya pada aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.(**)